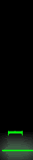MEMBANGUN SIKAP KRITIS ATAS TUDUHAN ‘MAKAR’ TERHADAP ORANG PAPUA
(BELAJAR DARI ‘TUDUHAN MAKAR’ PADA PASCA KONGRES RAKYAT PAPUA III)
Oleh: Yohanes Kayame[1]
Pertanyaan yang muncul dari topik masalah di atas adalah bahwa apakah dalam kerangka HAM dan pengertian tentang makar terkait tuduhan “makar” kepada orang Papua selama ini termasuk insiden pasca-Kongres Rakyat Papua III, dapat dibenarkan? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka dalam tulisan ini dikemukakan beberapa hal mendasar untuk memperjelas argumentasinya. Pertama-tama perlu diketahui bahwa masalah Papua yang sudah dan sedang terjadi adalah masalah yang perlu ditangani bersama. Kongres Rakyat Papua III tanggal 17-19 Oktober 2011 di Abepura (selanjutnya disebut KRP III) dilaksanakan karena ada sejumlah akar permasalahan yang belum diselesaikan. Orang Papua tidak mungkin melakukan KRP III tanpa ada akar permasalahan yang sudah dan sedang terjadi. Namun sayangnya para penegak keadilan dan kebenaran (orang Papua) ditangkap pada pasca KRP III dan kemudian distigma “makar”. Pertanyaannya, bukankah KRP III merupakan ekspresi masyarakat Indonesia dalam Negara RI yang kini mengedepankan demokrasi? Di manakah martabat kemanusiaan sebagai ciptaan Tuhan? Bagaimanakah stigma-stigma “makar” ini dapat dibenarkan berdasarkan pengertian makar dan dari kerangka HAM?.
Tuduhan ‘Makar’
Sebelum pasca KRP III, anak negeri Papua sudah banyak distigma “makar”. Kini orang Papua mendapat giliran stigma, tuduhan, dan hukuman karena “makar” dalam KRP III. Polda Papua, dalam hal ini Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Kombes Wahyono, di Jayapura, Kamis (20/10/2011), mengatakan bahwa penangkapan kelima tersangka terkait KRP III dinilai makar dan satu di antaranya terbukti membawa senjata tajam. Mereka itu adalah: Forkorus Yaboisembut, Edison Gladius Waromi, August Makbrawen Sananay Kraar, Dominikus Sorabut, dan Gat Wenda. Demikian pula, Pangdam XVIII/ Cendrawasih Mayor Jenderal TNI Erfi Triassunu mengatakan perlunya ‘tindak tegas perbuatan makar di Papua’).[2] Apakah stigmanisasi “makar” ini dapat dibenarkan?
Apa itu Makar dan Bagaimana dalam Kerangka HAM, dan dari Lembaga Kemanusiaan RI?
Makar, (dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah “(n) (1) akal busuk; tipu muslihat: segala -- nya itu sudah diketahui lawannya; (2) perbuatan (usaha) dng maksud hendak menyerang (membunuh) orang, dsb: krn -- menghilangkan nyawa seseorang, ia dihukum; (3) perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yg sah: ia dituduh melakukan – (n) makar: kaku dan keras (tt buah-buahan); bangkar”.[3]
Dengan definisi ini, kita bisa menyimpulkan dua pengertian makar, pengertian dari perspektif hukum dan kemanusiaan. Dari segi hukum, seseorang bertindak melawan pemerintahan dengan tindakan fisik maupun perkataan dan kemudian untuk membentuk suatu negara. Ini bisa dibenarkan. Namun untuk konteks Papua sangat kontras karena terkait dengan pelanggaran HAM atas perjuangan bangsa Papua (rekayasa Pepera 1969). Sedangkan dari segi kemanusiaan, seseorang dikatakan makar bila bertindak melawan kodrat kemanusiaannya secara irasional, immoral terhadap sesamanya, serta tidak menghargai dan mengakui harkat, martabat dan keberadaan sesamanya sebagai manusia yang mempunyai keinginan dan harapan akan masa depan.
Sangat terkait erat juga dengan ketetapan-ketetapan HAM, yakni hak orang untuk berekspresi, mengemukakan pendapat, hak untuk memiliki dan hak untuk mengungkapkan pendapat dalam Negara demokrasi. Lebih lanjut dalam piagam HAM PBB dikatakan pada pasal 15 ayat 1 bahwa setiap orang berhak untuk memiliki suatu kebangsaan, dan ayat 2, tak seorangpun boleh dicabut hak kebangsaan itu, dan ditolak haknya untuk merubah kebangsaan.[4]
Selain itu, terkait pelanggaran HAM tersebut Kontras Papua, menilai bahwa TNI/Polri telah melakukan pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen II pasal 28 ayat 3 bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Juga bertentangan dengan UU No. 12 tahun 2005 tentang pengesahan Konvensi Hak-hak Sipil Politik dan Pasal 21 mengenai kebebasan hak untuk berkumpul secara damai. Aparat TNI/ POLRI memandang bahwa tindakan mereka telah melanggar hukum, maka prosedur hukum harus dikedepankan, pemanggilan secara prosedural harus dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Dengan demikian, dikhawatirkan oleh Kontras Papua bahwa akan semakin memperburuk tingkat kekecewaan masyarakat Papua terhadap Pemerintah Indonesia. Lebih-lebih, tuduhan makar yang merupakan salah satu modus kriminalisasi terhadap setiap aspirasi politik Papua.[5]
Kontras Papua juga mempertanyakan keterlibatan TNI dalam operasi pembubaran paksa KRP III. Dikatakan, menurut aturan, keterlibatan TNI seharusnya mendapatkan persetujuan dari Presiden dan disetujui oleh DPR. "Patut diduga bahwa keterlibatan TNI adalah ilegal, mengingat keterlibatan TNI tersebut harus mendapat persetujuan dari Presiden dan disetujui oleh DPR dalam konteks gelar pasukan. Bagaimana ini dapat dilihat? Dan juga dari aspek kemanusiaan atas peristiwa-peristiwa makar/ pelanggaran HAM yang sudah terjadi di Papua itu?.
Sekilas Menelusuri kembali Pelanggaran HAM di Papua sebagai ‘Tindakan Makar’
Dalam KRP III dibicarakan sejumlah hal berkaitan dengan hak-hak dasar orang Papua yang diabaikan dan tidak diperhatikan. Terutama kemerdekaan bangsa Papua yang dideklarasikan pada tahun 1961. Namun kemerdekaannya, dimanipulasi atau direkayasa oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1963-1969.[6] Pepera menurut Drooglever adalah suatu tindakan Indonesia yang abstrak, tidak mendalam, tidak akurat.[7]
Dalam KRP I dan II menuntut tindakan itu, yakni tindakan yang dimanipulasi, direkayasa, tindakan makar, tipu muslihat, akal busuk, dan perlawananan, dan pembunuhan yang dilakukan. Pemerintah Indonesia bertindak tidak sesuai dengan amanat perjanjian New York Agreement 1962 tetapi Indonesia sibuk dengan memenangkan PEPERA 1969 dengan melakukan berbagai terror, intimidasi, penangkapan, kekerasaan, pembunuhan, dan berbagai manipulasi sosial politik terhadap masyarakat Papua yang mempertahankan haknya. Karena itu, dikatakan PEPERA tidak hanya cacat hukum tetapi juga cacat secara moral. Dan PEPERA merupakan hasil rekayasa politik oleh Indonesia. Disinilah dapat kami katakan bahwa terjadi kasus makar. Dan lebih para lagi dengan sejumlah operasi militer (Operasi Sadar, Bharatayudha, Wibawa, Gelang, dll).
Dengan tindakan militer demikian itu, maka banyak manusia Papua yang dibunuh. Organisasi Hak Asasi Manusia Internasional dan Lokal memperkirakan bahwa 100.000 orang Papua telah dibunuh oleh Pasukan Keamanan Indonesia; belum terhitung yang hilang di hutan dan mati kelaparan dll.[8] Disanalah terjadi pembunuhan, makar, yakni perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang, dsb: krn -- menghilangkan nyawa seseorang. Di sanalah nampak adanya tindakan ketidakadilan dan ketidakbenaran bahkan pelanggaran HAM berat terjadi. Sesamanya dipandang sebagai objek dalam kewenangannya dan menuduh, menahan, mengadili dan memenjarahkan. Mekanisme hukum yang ada ini digunakan untuk melindungi kepentingannya. Hukum tidak digunakan demi kemanusiaan. Aktualisasi/ stigmanisasi ‘makar’ menjadi tidak jelas dan tidak sesuai dengan yang tersurat.
Dengan berjalannya situasi demikian, maka pada tahun 1999 orang mulai berbicara masalah kemerdekaan bangsa Papua. Orang Papua mulai berbicara karena merasa asing di negerinya sendiri. Orang Papua dalam sejumlah hal dinomorduakan. Orang Papua selalu dicap ‘makar’ dan ‘separatis’. Setiap perjuangan orang Papua, yakni suara-suara masyarakat Papua dibungkam, diinjak, dicaci-maki dan tidak didengarkan.
Oleh karena itu, Kongres Rakyat Papua II dibicarakan untuk menata masa depan politik, sosial, dan kebudayaan masyarakat Papua. Para penegak keadilan dan kebenaran dalam Konggres II mengekspresikan agar hak-hak dasar orang Papua dapat diperhatikan, baik di tingkat nasional maupun dunia internasional. Namun sayangnya bahwa secara interen perbuatan mereka dikategorikan ‘makar’. Dan Kongres Rakyat Papua II ini dianggap tidak memiliki dasar hukum oleh Megawati Soekarno Putri.[9]
Perlunya Klarifikasi atas Hukum dan Tindakan Makar di Papua
Undang-undang pidana yang dibuat Indonesia perlu diklarifikasi. Salah satunya dalam Pasal 104 Undang-Undang Pidana dikatakan: ‘Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun’.[10] Demikianpun pasal 106 KUHP ‘makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan bagian negara dengan yang lain’. Dalam konteks Papua, aktualisasi makar sangat kontradiksi dan terkesan subyektif. Artinya, orang Papua dianggap makar, sementara para TNI dan POLRI pelaku makar berat tidak diberi pemahaman dan tidak dihukum. Padahal mereka melakukan makar, sudah melanggar HAM, di mana tindakan mereka tidak melihat pada aspek kemanusiaan.
Pelanggaran HAM tidak bisa dibendung oleh hukum Negara. Juga terkait kejadian yang terjadi pada pasca KRP III merupakan peristiwa pelanggaran HAM berat, dan itu merupakan perbuatan makar. Maka pihak TNI dan POLRI harus bertanggung jawab karena sudah melanggar HAM. Juga sudah melanggar ajaran moral, yakni ajaran agamanya. Pihak TNI dan POLRI telah melakukan aksi yang tidak manusiawi, dan yang tidak bermartabat di Negara yang demokratis ini. Mereka telah melakukan aksi yang brutal, dan tidak manusiawi terhadap orang Papua bahkan orang non Papua. Mereka perlu ditindak tegas karena telah melanggar Hukum Internasinal (HAM). Karena dalam negara yang demokratis, KRP III ini dilakukan, namun akhirnya diinterogasi dan lain-lain terhadap ratusan orang Papua, termasuk beberapa orang non Papua, bahkan 7 orang Papua ditembak mati, yakni: Damianus Daniel Kedepa (mhs. Ilmu Hukum Umel Mandiri Jayapura), Maks Yeuw dan Yakob Sabon Sabra (masyarakat sipil), dan 2 orang Sorong dan 2 orang Wamena. Dan juga sejumlah tindakan kekerasan dan pembunuhan lain pada pasca KRP III.
Upaya Penegakkan Makar yang Bermartabat dalam Kerangka HAM di Papua
Perjuangan untuk meneggakkan keadilan dan kebenaran atas pelanggaran HAM di Papua, tidak akan pernah dihentikan oleh orang Papua dan lembaga-lembaga kemanusiaan nasional maupun Internasional. Perjuangan dalam peneggakkan HAM tetap akan diperjuangkan. Dan KRP III dilaksanakan untuk membicarakan masalah pelanggaran HAM yang harus dibicarakan. Dalam dunia dan Negara demokrasi, hal ini perlu dikedepankan agar dapat diekspresikan hak kebebasannya. Dalam kegiatan KRP III, secara implisit berbicara soal implementasi OTSUS di Papua yang tidak dinikmati oleh masyarakat Papua, walaupun secara eksplisit terungkap Deklarasi Bangsa Papua.
Akibatnya dituduh ‘makar’. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa dua kutup yang tidak bisa ditemukan. Penyoal keutuhan bangsa menuding penyoal kemanusian dengan mengungkapkan pelaku ‘makar’. Dua kutup yang nampak tidak dapat ditemukan ini bisa diselesaikan hanya dengan melihat tindakan itu sebagai persoalan mutlak atau relatif. Kalau melihat tindakan dari segi relatif, anak bangsa ini telah menutup mata terhadap persoalan kemanusian. Kapan bangsa ini akan menghargai dan mengakui martabat kemanusiaan, kebebasan berekspresi dan persoalan-persoalan mutlak bagi orang Papua? Apakah hukum relatif lebih penting dari pada martabat kemanusiaan, hukum mutlak? Apakah tindakan pembunuhan, tipu muslihat terhadap orang Papua bukan merupakan pelanggaran HAM, tindakan makar dan melanggar Hukum Allah dalam agamanya? Dalam Hak Asasi Manusia ditekankan soal menghargai martabat manusia, bab 3 hak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan, bab 5 larangan penganiyaan, bab 19 hak untuk kebebasan berpendapat, dan lain-lain.[11]
Berdasarkan ketentuan-ketentuan HAM, maka pihak militer di Papua jangan memutarbalikkan ungkapan ‘makar’ terhadap orang Papua. Jangan melihat kata ‘makar’ dari satu pengertian saja. Sebenarnya orang Papua bukan ‘makar’. Mereka memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Orang Papua bukan merongrong Negara NKRI (“makar”), tetapi untuk memulihkan, dan mengakui secara damai haknya sebagai manusia yang bebas, yang menjunjung tinggi HAM.[12] Dan lebih dari itu juga, kita ingin agar martabat kemanusiaannya dihargai, tidak ingin dianiaya dan diteror, dan ingin agar hak kebebasan berpendapat dan kebebasan hidup dihargai dan diakui serta aplikasi HAM dikedepankan dan pelanggaran HAM di Negeri Cenderawasih tidak terjadi lagi. Kata lain, nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai budaya dikedepankan. Dengan demikian, orang di Papua, secara khusus Orang Papua, mengalami kebebasan, kebahagiaan atau keselamatan di atas tanah Papua ini.
Rekomendasi
Sebagai penutup atas tulisan ini, saya mengemukakan beberapa poin penting sebagai rekomendasi. Pertama, Negara Indonesia dalam menangani kasus makar harus mengedepankan dan tetap menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan, karena selama ini orang Papua bukan melakukan tindakan makar. Kedua, Perlu melihat kembali apa itu makar yang sesungguhnya. Dan perlu diadakan peninjauan dan pengaturan kembali atas implementasi undang-undang pidana (makar); apakah sejalan dengan bergulirnya reformasi di Negara demokrasi RI di Papua. Ketiga, Perlu diadakan pendidikan, pelatihan dan sosialisasi tentang pentingnya HAM; dan berbagai ketentuan nasional dan Internasional tentang HAM kepada TNI dan POLRI, juga kepada aparat penegak hukum. Keempat, Negara Indonesia membuka diri dan menyediakan kesempatan untuk mengadakan dialog damai, dan bersedia mendengar berbagai pendapat aspirasi dari berbagai komponen masyarakat, terutama dari orang Papua; dan dialog ini difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral. Dan kelima, masalah Papua adalah masalah Gereja; maka tugas kenabiaan Kristus perlu dijiwai dan diaktualisasikan dalam realitas sosial di Papua. Gereja dipanggil untuk menegakkan keadilan dan kebenaran.[13] Dan dalam hal ini aktualisasinya perlu direfleksikan model pastoral yang sangat relevan untuk meminimalisir problem realitas sosial di Papua.
Penulis: Mahasiswa Pasca Sarjana Pada STFT-Fajar Timur Abepura-PAPUA.
SUMBER
Buku
Agus Alua Alua, M.Th., Papua Barat dari Pangkuan ke Pangkuan, (Abepura: Biro Penelitian, STFT Fajar Timur), 2006.
Dr. Neles Tebay, Pr., Upaya Lintas Agama demi Perdamaian di Papua Barat (hasil terjemahan bahasa Indonesia dari versi asli bahasa Inggris Interfaith Endeavours for Peace in West Papua), Missio, Seri Human Rights no. 24, Aachean, 2006.
Departemen Pendidikan Nasional - Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi ke- 3), (Jakarta: Balai Pustaka), 2001.
Michael J. Schultheis SJ, dkk, Pokok-Pokok Ajaran Sosial Gereja, (Yogyakarta: Kanisius), 1988.
P.J. Drooglever, Tindakan Pilihan Bebas Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri, (Yogyakarta: Kanisius), 2010.
Siegfried Zoller, The Culture of the Papuans in Transition (sebuah artikel) dalam buku, Economic, dan Cultural Rights in West-Papua, (Germany: Feadvus-Verle), 2005.
Makalah (Seminar)
Forkorus Yaboisembut, S.Pd., Makar Menurut Perpektif Adat (Makalah yang dibawakan dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Wirewit Studi Centre (WSC), di STFT Fajar Timur Abepura, 27 Februari 2010.
M. Ferry Kareth, M.Hum., Ketentuan-Ketentuan Mengenai HAM dalam sebuah makalahnya yang berjudul ‘Makar’ Suatu Ungkapan Kontroversi – Perpektif Akademisi, (dibawakan dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Wirewit Studi Centre (WSC), di STFT Fajar Timur, Abepura, 27 Februari 2010.
Media Cetak dan Internet
Cenderawasih Pos tanggal 24/10/2011.
Pernyataan Umum PBB tentang Hak Asasi Manusia, dalam http://id.wikisource.org/wiki/Pernyataan_Umum_tentang_Hak-Hak_Asasi_Manusia. Diakses 14 November 2011.
Undang-Undang Pidana, Buku Kedua dalam http://id.wikisource.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Pidana/Buku_Kedua. Diakses, 14 November 2011.
[2] Halaman Depan/ Berita Utama Cenderawasih Pos tanggal 24/10/2011.
[3] Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi ke- 3), (Jakarta: Balai Pustaka), 2001, hal. 702.
[4] Pernyataan umum PBB tentang Hak Asasi Manusia, dalam http://id.wikisource.org/wiki/Pernyataan_ Umum_ tentang_ Hak-Hak_Asasi_Manusia. Diakses 14 November 2011.
[5] Internet………………………..
[6] Agus Alue Alua, M.Th., Papua Barat dari Pangkuan ke Pangkuan, (Abepura: Biro Penelitian, STFT Fajar Timur), 2006, hal. 53-54.
[7] P.J. Drooglever, Tindakan Pilihan Bebas Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri, (Yogyakarta: Kanisius), 2010, hal. 563-579.
[8] Dr. Neles Tebay, Pr., Upaya Lintas Agama demi Perdamaian di Papua Barat (hasil terjemahan bahasa Indonesia dari versi asli bahasa Inggris Interfaith Endeavours for Peace in West Papua), Missio, Seri Human Rights no. 24, Aachean, 2006, hal. 4-7.
[9] Siegfried Zoller, The Culture of the Papuans in Transition (sebuah artikel) dalam buku, Economic, dan Cultural Rights in West-Papua, (Germany: Feadvus-Verle), 2005, pg. 39-45.
[10] Undang-Undang Pidana, Buku Kedua dalam http://id.wikisource.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_ Pidana/Buku_Kedua. Diakses, 14 November 2011.
[11] M. Ferry Kareth, M.Hum., Ketentuan-Ketentuan Mengenai HAM dalam sebuah makalahnya yang berjudul Makar’ Suatu Ungkapan Kontroversi – Perpektif Akademisi, (yang dibawakan dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Wirewit Studi Centre (WSC), di STFT Fajar Timur Abepura, 27 Februari 2010, hal. 2-3.
[12] Forkorus Yaboisembut, Makar Menurut Perpektif Adat (Makalah yang dibawakan dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Wirewit Studi Centre (WSC), di STFT Fajar Timur Abepura, 27 Februari 2010, hal. 5-6.
[13] Menegakkan Keadilan di Dunia, Pesan Injil dan Misi Kristus, (Pernyataan Sidone Para Uskup tahun 1971), dalam Pokok-Pokok Ajaran Sosial Gereja (Yogyakarta: Kanisius), 1988, hal. 87-90.