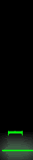OTSUS GAGAL, PAPUA PERLU MERDEKA (?)
Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua diberikan sebagai jawaban pemerintah Indonesia terhadap maraknya tuntutan kemerdekaan yang ditandai dengan pengibaran bendera Bintang Kejora di beberapa kabupaten di Papua sejak 1998. Alasan tuntutan tersebut, menurut Pemerintah, disebabkan oleh kegagalan kebijakan pembangunan (Theo van den Broek, dkk.: 2003: 164), sehingga Otsus diberikan sebagai jawaban untuk menyelesaikan konflik Papua. Namun, benarkah penilaian pemerintah itu?
Dalam tulisan ini hendak diuraikan sejauh mana persoalan di Papua disebabkan oleh kegagalan pembangunan? Mungkinkah ada persoalan lain yang lebih mendasar daripada kegagalan pembangunan? Apakah Otsus menjawab persoalan Papua atau sebaliknya? Bagaimana solusi yang perlu diambil dalam menyelesaikan konflik Papua? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan menjadi fokus perhatian dalam tulisan ini.
Otsus Gagal, Kekerasan Terus Terjadi di Papua
”Inti tawaran Otsus bagi Provinsi Papua”, tulis Theo dkk, ”tercipta dari pandangan resmi yang berkembang dan disosialisasikan oleh kalangan pejabat Pemerintah bahwa persoalan di Papua berakar dari gagalnya kebijakan pembangunan di wilayah tersebut” (ibid. 164). Selain itu, Otsus juga diberikan sebagai tanggapan atas munculnya unjuk rasa dan pengibaran bendera Bintang Kejora di berbagai kabupaten di Papua selama 1998. Tawaran Otsus bagi Provinsi Papua juga didasarkan pada pandangan pemerintah yang tidak boleh diganggu gugat, bahwa Papua merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Inspirasi lain dari tawaran Otsus merupakan kebijakan nasional yang harus berlaku bagi semua Provinsi di Indonesia. Semua ini merupakan gagasan dasar dari pemberian Otsus bagi Provinsi Papua.
Niat baik pemerintah memberikan Otsus bagi Provinsi Papua merupakan hal yang sangat positif. Namun, adalah keliru jika Otsus diberikan hanya untuk menyelesaikan konflik Papua yang diredusir sebagai kegagalan pembangunan. Pemerintah menilai bahwa konflik yang timbul di Papua berasal dari kegagalan pembangunan. Dengan demikian logikanya adalah karena kegagalan pembangunan, orang asli Papua menuntut kemerdekaan, yang ditandai dengan pengibaran bendera Bintang Kejora? Penilaian pemerintah ini tampak dengan amat jelas ketika UU Otsus diimplementasikan di Papua.
UU Otsus diidentikan dengan uang. Otsus adalah uang, sehingga hampir setiap tahun dana triliunan rupiah dikucurkan ke Papua. Masyarakat selalu antusias menerima pencairan dana Otsus. Dana Otsus yang diberikan itu jumlahnya tidak sedikit. Misalnya, anggaran dana Otsus dari tahun 2002 sejak 2007 masing-masing adalah; 1,2 triliun (2000), 1,3 triliun (2003), 1,4 triliun (2004), 1,5 triliun (2005), 1,7 triliun (2006), dan 3,2 triliun (2007). Jadi jumlah total anggaran dana Otsus untuk Papua sejak tahun 2000 hingga 2007 sebanyak 10,3 triliun. (sumber data: Buletin Keuskupan Manokwari-Sorong No 33/September 2007, hal 42; lihat juga catatan kaki dari tulisan Bisei: 2007: 18-19). Dana yang begitu banyak ini belum terhitung dengan anggaran dana Otsus 2008 dan 2009. Banyaknya dana yang diberikan bagi Provinsi Papua dan Papua Barat tersebut dipandang sebagai upaya untuk menyejahterakan orang asli Papua. Singkatnya karena kegagalan pembangunan, dana Otsus harus lebih banyak diberikan untuk menyejahterakan orang asli Papua.
Meskipun persoalan di Papua disebabkan oleh kegagalan pembangunan, Otsus sendiri tidak berhasil menyejahterakan orang asli Papua. Nyatanya sejak Otsus diberlakukan, pertumbuhan ekonomi masyarakat justru menurun drastis bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi sebelum Otsus. Menurut LIPI pertumbuhan ekonomi tahun 1995, 1996, 1997, 1998 mencapai 20,18%, 13,87%, 7,42%, dan 12,72%; sedangkan pertumbuhan ekonomi sesudah Otsus diimplementasikan pada tahun 2002, 2003, 2004, hanya mencapai 8,7%, 2,96%, dan 0,53%. (Widjojo, 2009: 14)
Padahal dana Otsus yang dikucurkan ke Papua sangat tinggi belum terhitung uang yang dikelola lembaga-lembaga non-pemerintah dan perusahan-perusahan besar. Tetapi, nyatanya kemiskinan sangat tinggi di Papua. Tingkat kemiskinan yang amat tinggi ini oleh Bisei disebut sebagai kemiskinan absolut dan ekstrim. Bersifat absolut karena hal-hal pokok (basic needs) yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup nyaris tak terpenuhi. Contohnya terjadi bencana kelaparan di beberapa kabupaten di Papua seperti Tolikara, Yahukimo, Jayawijya, Puncak Jaya dan Paniai. Buruknya kesehatan yang menimbulkan berbagai penyakit yang diderita rakyat dan angka kematian cukup tinggi. Kemiskinan bersifat ekstrim karena keterbelakangan rakyat Papua dalam hal pengolaan teknologi akibat pengetahuan yang rendah, tingginya angka buta huruf, keterampilan yang terbatas dan keahlian yang minim. Untuk mengolah sumber daya alam, rakyat hanya menggunakan tenaga otot dan pengetahuan seadanya yang sudah diwariskan kepada mereka (Bisei: 2007: 18). Karena itu, kemiskinan di Papua yang bersifat absolut dan ekstrim ini merupakan suatu bentuk penindasan yang mengekang rakyat Papua untuk keluar dari kondisi hidup yang terpuruk dan karenanya menurunkan derajat dan martabat rakyat Papua ke titik yang tidak manusiawi (ibid).
Jadi kalau konflik di Papua hanya direduksi ke dalam kegagalan pembangunan, maka Otsus jelas-jelas gagal menyejahterakan orang asli Papua. Bila Otsus gagal menyejahterakan orang asli Papua, maka tuntutan kemerdekaan tidak pernah selesai, sebab mereka belum sejahtera. Akibatnya konflik pun tidak akan pernah selesai. Tuntutan kemerdekaan dan pengibaran bendera Bintang Kejora pun tidak akan berhenti.
Konflik di Papua bukan hanya dikarenakan oleh kegagalan pembangunan saja. Konflik di Papua lebih pada persoalan sejarah dan identitas bangsa Papua. Persoalan sejarah integrasi dan identitas bangsa merupakan persoalan dasar yang mendorong timbulnya upaya untuk merdeka. Jadi apabila pemerintah pusat dapat menyelesaikan persoalan sejarah integrasi dan identitas bangsa Papua, maka tuntutan kemerdekaan Papua bisa dikurangi bahkan tidak lagi terjadi. Para perumus UU Otsus tidak memperhatikan persoalan fundamental ini. Mereka mengira bahwa konflik di Papua diakibatkan oleh kegagalan pembangunan dan mengabaikan sisi fundamental dari konflik Papua.
Hal ini terbukti bahwa dalam masa pelaksanaan UU Otsus pun, kekerasan terhadap rakyat Papua terjadi. Kekerasan Wasior 2003 yang mengorbankan 4 orang dan kasus Wamena 2005 yang menewaskan 9 orang merupakan bukti kuat akar konflik di Papua. Selain itu hampir setiap saat kita mendengar, melihat dan membaca pada media massa baik elektronik maupun surat kabar bahwa terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak keamanan negara kepada orang asli Papua.
Kekerasan yang dialami oleh rakyat Papua sejak Papua berintegrasi dengan NKRI 1 Mei 1963 juga merupakan bentuk lain potensi konflik di Papua. Operasi militer dari tahun 1965-1969; 1969,1977; 1981-1985; dan dilanjutkan pada 2003-2005 (bdk. Neles Tebay: 2008; 133) Semua ini sebetulnya menunjukkan tentang akar persoalan di Papua. Kekerasan akibat politik negara terhadap rakyat Papua menyebabkan terus adanya tuntutan untuk merdeka dan pengibaran bendera Bintang Kejora.
Bukan hanya kekerasan akibat politik negara, melainkan juga kurangnya penghargaan atas martabat orang asli Papua melalui ekspresi budaya mereka. Faktor kultural sangat menjiwai kehidupan orang asli Papua. Melarang mereka untuk tidak mempertunjukkan simbol-simbol kedaerahan mereka, berarti tidak menghargai mereka. Seorang aktivis damai di Papua dalam sebuah diskusi tentang HAM berkomentar ”pemerintah Indonesia tidak mau memperhatikan Mas-Mas Papua tetapi Emas Papua”. Artinya keinginan untuk memberdayakan orang Papua kurang dipedulikan oleh pemerintah Indonesia, tapi yang diperlukan dari Papua adalah emas atau harta kekayaan. Singkatnya martabat orang Papua sebagai manusia yang berbudaya tidak dipedulikan oleh pemerintah, yang penting bagi Pemerintah adalah emas dan kekayaan alamnya.
Kurangnya penghargaan terhadap martabat orang asli Papua terlihat jelas dengan adanya larangan untuk tidak menggunakan lambang-lambang, simbol-simbol kedaerahan yang mengarah pada ancaman keutuhan NKRI. Lambang bendera Bintang Kejora pada tas-tas (noken), pakaian, topi, merupakan salah satu contoh isu yang dinilai mengancam keutuhan NKRI. Selain itu hampir di semua kantor pemerintahan dan perusahan-perusahan swasta didominasi oleh orang non-Papua. Warga asli Papua hanya berdiri sebagai penonton karena mereka tidak mampu bersaing dengan warga pendatang. Di bidang ekonomi, warga pendatang lebih unggul ketimbang warga asli Papua. Salah satu contoh konkret terlihat di Pasar Youtefa di mana hampir semua kios dan tempat jualan diduduki oleh warga pendatang. Sementara Mama-Mama Papua hanya berjualan di atas tanah. Mereka juga banyak berjualan di emperan toko atau ruko-ruko. Kenyataan ini menunjukkan adanya sikap marginalisasi terhadap orang asli Papua.
Sikap marginalisasi ini didukung oleh pemerintah Indonesia melalui program transmigrasi yang mendatangkan banyak orang dari luar Papua. (bdk Bless: 2001: 40). Kedatangan kaum pendatang menyebabkan adanya sikap minder dari orang asli Papua, sehingga mereka akan tergeser ke pinggiran kota. Jadi, inti persoalan di Papua bukan hanya terletak pada kegagalan pembangunan, melainkan juga sejarah integrasi dan identitas bangsa serta marginalisasi orang asli Papua. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Otsus gagal menyelesaikan konflik Papua. Kegagalan Otsus dalam menyelesaikan konflik Papua, bagi saya, menjadi bukti nyata bahwa Papua perlu merdeka.
Papua Perlu Merdeka (?)
Maksud Papua perlu merdeka bukan berarti terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Papua perlu merdeka karena otsus telah diberikan seluas-luasnya bagi Provinsi Papua, namun persoalan di Papua masih terus terjadi. Persoalan yang terus terjadi menunjukkan adanya `ketidakberesan` dalam pelaksanaan UU Otsus sehingga Otsus disebut gagal. `Ketidakberesan` pelaksanaan Otsus diakibatkan oleh belum adanya kesamaan persepsi antara pemerintah Indonesia dan orang asli Papua dalam menyelesaikan konflik Papua dan kurangnya penghormatan terhadap martabat kemanusian orang Papua. Dua hal dasariah ini belum diperhatikan dengan sungguh sehingga Otsus diberikan, tetapi tidak menyelesaikan persoalan.
Pertama, belum adanya kesamaan persepsi antara pemerintah Indonesia dan orang asli Papua dalam menyelesaikan konflik Papua. Pemerintah Indonesia mengira bahwa konflik di Papua dapat diatasi melalui pendekatan keamanan. Karena itu, selama Papua berintegrasi dengan NKRI terjadi operasi militer besar-besaran di Papua. Sedikitnya terdapat dua belas operasi militer di Papua sejak 1 Mei 1963 hingga kini.
Operasi Sadar merupakan operasi pertama yang dimulai tahun 1965 dan berakhir dua tahun kemudian. Operasi kedua disebut Operasi Brathayuda tahun 1967 dan menelan korban sekitar 3.500 orang. Operasi ketiga disebut Operasi Wibawa yang dilakukan sejak tahun 1969 dan menelan korban jiwa sekitar 30.000 jiwa antara tahun 1963-1969.
Operasi keempat dilaksanakan di Kabupaten Jayawijaya tahun 1977dan mengakibatkan 12.397 warga Papua meninggal dunia. Operasi kelima dikenal sebagai Operasi Sapu Bersih I dan II tahun 1981, yang menelan korban jiwa sedikitnya 1.000 orang di Kabupaten Jayapura dan 2.500 orang di Kabupaten Paniai. Tahun 1982, terjadi operasi keenam yang dikenal Operasi Galang I dan II, yang menyebabkan terbunuhnya ribuan jiwa. Operasi Tumpas merupakan operasi ketujuh dan berlangsung antara tahun 1983-1984.
Tahun 1985 terjadi lagi operasi Sapu Bersih yang dikenal sebagai operasi kedelapan. Dalam operasi kedelapan sedikitnya 517 jiwa dibunuh oleh TNI dan membumihanguskan sekitar 200 rumah. Operasi kesembilan dilakukan di Mapenduma tahun 1996, yang menyebabkan 35 orang Papua meninggal dunia, 14 perempuan diperkosa, 13 gereja dirusak dan 166 rumah dibumihanguskan, sementara 123 warga sipil meninggal akibat penyakit dan kelaparan setelah menyelamatkan diri ke dalam hutan.
Pada 1998 status Papua sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) dicabut oleh Indonesia, tetapi pengejaran terhadap orang Papua tetap berlanjut. Karena itu, operasi kesepuluh dilakukan tahun 2001 di Kabupaten Manokwari dan menyebabkan 4 orang dibunuh, 6 orang mengalami penyiksaan, 1 perempuan diperkosa dan 5 orang hilang.
Antara April sampai November 2003 terjadi lagi operasi di Wamena. Operasi di Wamena ini merupakan operasi kesebelas. Pada saat itu tentara menguasai seluruh kawasan, menghambat akses kelompok Gereja dan pekerja kemanusiaan untuk memberikan bantuan selama berlangsungnya operasi. Akibatnya 9 orang meninggal dunia, 38 orang mengalami penyiksaan dan 15 orang ditangkap tanpa alasan yang jelas.
Pada 2004 terjadi operasi kedua belas di Kabupaten Puncak Jaya yang menyebabkan 6.000 dari 27 desa menyelamatkan diri ke hutan, dan 35 diantaranya termasuk 13 anak-anak meninggal di kamp pengungsian yang dibangun di sana. Seluruh daerah tertutup untuk para pekerja kemanusiaan (Tebay, 2005: 5-6).
Di sini tampak dengan jelas bahwa penyelesaian konflik Papua melalui pendekatan militer tidak pernah menyelesaikan konflik, sebaliknya menambah persoalan. Namun, pandangan pemerintah Indonesia bahwa konflik di Papua akan aman bila kaum separatis telah dihabiskan. Karena itu, tujuan operasi militer yang dilakukan adalah memberantas orang asli Papua yang dianggap separatis oleh pemerintah Indonesia (ibid. 6).
Persepsi semacam ini tidak pernah mendatangkan kedamaian bagi orang asli Papua. Masyarakat akan tetap memandang pemerintah sebagai penjajah dan pembunuh. Ada ketakutan warga asli untuk mendekatkan diri dengan pemerintah yang termanifestasi melalui militer. Akibatnya niat baik pemerintah untuk memberdayakan orang asli Papua tidak direspon positif. Warga asli memandang niat baik pemerintah sebagai upaya untuk menghabiskan mereka. Salah satu contoh konkret adalah Otonomi Khusus. Sejak Otsus diberikan bagi Provinsi Papua, terjadi pro-dan kontra antara warga asli Papua sendiri. Kebanyakan dari warga asli tidak menyetujui `niat baik pemerintah itu`. Bagi warga, Otsus hanya ”gula-gula politik” pemerintah Indonesia untuk menjauhkan warga dari persoalan dasar di Papua.
Dari pihak warga asli, ada ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Ketika pemerintah berupaya untuk menyejahterakan warga, warga memandang `niat baik pemerintah itu` sebagai upaya menjauhkan mereka dari berbagai ingatan penderitaan di masa lalu. Warga selalu berpandangan negatif terhadap pemerintah dikala pemerintah mau menolong mereka. Pikiran negatif masyarakat bermula dari pengalaman akan penderitaan yang mereka alami selama bertahun-tahun. Karena itu tidak heran bila warga sepakat untuk mengembalikan Otsus kepada pemerintah Indonesia.
Untuk menyelesaikan berbagai persoalan ini, maka harus ada kesamaan persepsi antara pemerintah Indonesia dan warga asli Papua. Salah satu bentuk konkret untuk membangun persamaan persepsi yakni melalui dialog. Buku karangan Dr Neles Tebay ”Dialog Jakarta-Papua: Sebuah Perspektif Papua” merupakan salah satu solusi ke arah itu. Harus ada dialog Jakarta dan Papua supaya pemerintah pusat mengetahui dengan pasti apa persoalan dasariah yang terjadi di Papua. Dengan demikian, persoalan di Papua akan terselesaikan dengan baik, adil, demokratis dan bermartabat.
Kedua, kalau dialog sudah dimulai, maka harus ada penghormatan terhadap martabat kemanusiaan orang Papua. Martabat kemanusiaan orang Papua selama bertahun-tahun diinjak-injak dengan adanya operasi militer. Menyadari hal ini, pemerintah menawarkan Otonomi Khusus bagi Papua untuk menghormati harkat dan martabat mereka. Tetapi, selama UU Otsus dilaksanakan, kekerasan terhadap warga asli Papua pun tak kunjung henti. UU Otsus dilaksanakan secara sah pada 2002, namun pada 2003 terjadi kekerasan di Wasior dan pada 2005 di Wamena. Kasus Wasior 2003 menewaskan 4 orang dan kasus Wamena 2005 menewaskan 9 orang. Kenyataan ini diperkuat lagi dengan adanya pelbagai macam kekerasan, intimindasi, peneroran yang terjadi selama tahun-tahun pelaksaanaan UU Otsus.
Sikap seperti ini memperlihatkan adanya ketidakhormatan terhadap martabat manusia. Harkat dan martabat manusia karena alasan politik dapat diperlakukan dengan tidak adil dan manusiawi. Pihak yang berkuasa dapat melakukan tindakan semena-mena terhadap pihak yang lemah. Karena itu, sikap menghormati dan menghargai martabat kemanusiaan orang lain perlu dijunjung tinggi.
Sikap menghormati dan menghargai bukan hanya kepada manusia semata, melainkan juga budaya mereka. Persoalan yang muncul kerapkali diakibatkan oleh kurangnya penghargaan atas nilai budaya mereka. Nilai adat yang dulunya mengatur kehidupan bersama, sehingga segala sesuatu dapat berjalan lancar dan kelestarian hidup baik perorangan maupun kelompok terjamin (Broek, 2006: 8). Namun, kini semuanya telah berubah. Nilai budaya masyarakat telah digantikan dengan kehendak nasionalisme pemerintah. Misalnya, perjuangan Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk menjadikan bendera Bintang Kejora dan simbol Burung Mambruk menjadi bendera dan simbol budaya orang Papua ditanggapi oleh PP No 77/2007 yang melarang penggunaan simbol-simbol separatis sebagai simbol-simbol budaya dan daerah (Widjojo, 2009:32).
Dengan demikian, bila ada kesamaan persepsi antara pemerintah Indonesia dan warga asli Papua melalui suatu dialog damai dan penghormatan, penghargaan, terhadap manusia dan budaya mereka, persoalan di Papua dapat terselesaikan dengan baik, adil, demokratis dan bermartabat.
Penutup
UU Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua telah diberikan. Salah satu alasan pemberian Otsus tersebut dikarenakan oleh kegagalan kebijakan pembangunan. Kerena alasan kegagalan pembangunan, dana Otsus diberikan bertriliun-triliun namun kenyataannya Otsus gagal menyejahterakan orang asli Papua. Sementara itu konflik di Papua terus terjadi. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa masalah di Papua bukan hanya kerena faktor kegagalan pembangunan, melainkan sejarah integrasi dan identitas bangsa, kekerasan politik negara, dan marginalisasi orang asli Papua. Dengan demikian, Papua perlu merdeka. Kemerdekaan Papua adalah bukan terlepas dari NKRI melainkan merdeka dalam arti adanya kesamaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat asli Papua dan adanya penghargaan terhadap martabat orang asli Papua sebagai manusia berbudaya.
Kepustakaan
Bisei, Abdon. ”Penderitaan Rakyat Papua Sengsara Yesus Masa Kini: Refleksi Soteriologi atas Penderitaan Rakyat Papua” dalam Limen, Th. 4, No 1 Oktober 2007.
Broek, Theo van den, dkk. Memoria Passionis di Papua: Kondisi Sosial Politik dan Hak Asasi Manusia 2001. Jayapura. SKP Jayapura dan LSPP Jakarta. 2003
-----------------., Membangun Budaya Damai dan Rekonsiliasi: Dasar Menangani Konflik di Papua. Jayapura. SKP Jayapura. 2006
Buletin Keuskupan Manokwari-Sorong No 33/September 2007.
Tebay, Neles., Interfaith Endeavours for Peace in West Papua, London: CIIR (Catholic Institute for Internasional Relations). 2005.
-----------------.,Papua: Its Problems and Possibilities for a Peaceful Solution, Jayapura: SKP Jayapura. 2008.
-----------------., Dialog Jakarta-Papua: Sebuah Perspektif Papua, Jayapura: SKP Jayapura, 2009.
Widjojo, Muridan S., (ed) Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future, Jakarta: Obor, LIPI, TiFA. 2009.