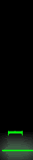Ketika Kisah Cinta Menembus Batasan Jarak
Santon Tekege, seminaris angkatan pertama KPA Nabire sekarang Frater Diosesan yang menjalani TOP, Tahun Orientasi Pastoral di Bomomani suatu ketika bertanya pada saya: “Bagaimana Pater bisa membuat banyak hal di Bomomani, bagaimana Pater bisa mencari orang-orang membantu pembangunan di Bomomani?” Suatu pertanyaan yang menarik, dan mungkin dilatari pikiran bahwa dana dari Jakarta mengalir deras ke suatu kampung terpencil di pedalaman Papua ini. Jawaban saya singkat saja waktu itu: “Pertama, saya percaya hanya orang biasa yang mengira ada sesuatu yang tidak mungkin; kedua, saya belajar dan bertanya pada orang yang lebih dulu berkarya di tempat ini; ketiga, saya membangun persahabatan dan pengharapan dengan orang-orang yang punya hati pada Papua.”
Dari Pertanyaan Seorang Frater
Saya menulis kisah ini dari pertanyaan seorang frater, lima belas tingkat di bawah saya, yang sebentar lagi 9 tahun menjadi imam. Namun kehadiran Fr. Santon di Bomomani dan angkatannya di beberapa wilayah misi pedalaman Keuskupan Timika untuk menjalani TOP, saya kira bukan suatu hal yang biasa-biasa saja walau kelihatannya demikian. TOPer tahun ini adalah buah kegigihan seorang Yesuit bernama Yusuf Suharyoso, yang nekat mendirikan KPA di Nabire di sela-sela kesibukan dan (saya tahu) kebingungannya menyelesaikan gereja paroki Kristus Sahabat Kita, Bukit Meriam – Nabire. Dan dia tidak mungkin sendirian banting tulang di situ, (saya tahu) ada Sr. Juliva SMSJ mengajar di seminari KPA perdana itu; (saya rasakan) kami terbakar semangat yang sama ketika Romo Yusuf mengundang untuk terlibat membagi ilmu dengan mereka.
Mengenang tahun-tahun awal tugas di Keuskupan Timika dan saya menemukan orang-orang yang sadar bahwa dirinya bukan orang biasa, orang-orang yang tidak mau tahu bahwa ada sesuatu yang tidak mungkin, orang-orang yang mati-matian menghayati dirinya adalah seorang misionaris. Jangan salahkan saya berpikir demikian, karena orang pertama yang menjumpai saya adalah Basilius Soedibya SJ; yang menjemput saya dan mengajak saya berputar-putar dengan Land Rover tuanya di kota seremeh Nabire. Tidak ada yang menarik di Nabire, tidak ada mall, tidak ada bioskop 21, tidak ada satu mobil sedanpun, tidak ada restoran enak dan terlebih lucu lagi tidak ada barang murah di Nabire. Ketertarikan itu muncul ketika di sudut kecil kaki Bukit Meriam, Romo Bas akhirnya menunjukkan suatu hal yang istimewa, pusat misi Yesuit. Istimewa karena tidak seperti yang saya bayangkan tentang misi para Yesuit ini.
Sejak masuk SMP Kolese Kanisius, saya mulai dididik Yesuit di daerah super elit di jalan Menteng Raya, sebuah sekolah yang tiap tahun diimpikan seribu lebih remaja Jakarta namun hanya puluhan orang saja diizinkan duduk di bangku belajar jati, yang bukan main antiknya. Waktu itu saya masih rasakan lantai marmer di aula tua yang sekarang auditorium bertingkat dua. Sementara tentang Romo Bas, dalam tugas terakhirnya di Jakarta saya kenal sebagai seorang Rektor Seminari Menengah Wacana Bhakti dan Kolese Gonzaga sekaligus, juga sekolah hebat bahkan untuk ukuran Jakarta sekalipun. Setahu saya, dulu Romo Bas hanya bergaul dengan orang-orang besar yang kekayaannya tidak habis tujuh turunan, orang-orang yang aroma harumnya saja sudah bikin iri bunga-bunga mawar di tama n depan Rektorat yang megah. Dan di Nabire, sebuah sekolah kumuh SMU Adhi Luhur sudah disebut sebagai kolese, sebuah rumah yang retak sana sini sudah menjadi pusat misi tarekat sebesar Serikat Yesus. Romo Bas gemar membanggakan bengkel kayu dan kandang babinya. Semua itu tidak membuat saya kagum sedikitpun sampai kemudian saya tahu bahwa tidak ada satupun bengkel furniture di Papua punya alat selengkap karya misi Yesuit ini; dan bahwa semua alat itu harus dibawa dengan sebuah Landing Ship Tank, sebuah alat perang, seperti alegori sebuah perjuangan yang harus segera saya hadapi juga setelah menatap paroki kosong di Bomomani.
n depan Rektorat yang megah. Dan di Nabire, sebuah sekolah kumuh SMU Adhi Luhur sudah disebut sebagai kolese, sebuah rumah yang retak sana sini sudah menjadi pusat misi tarekat sebesar Serikat Yesus. Romo Bas gemar membanggakan bengkel kayu dan kandang babinya. Semua itu tidak membuat saya kagum sedikitpun sampai kemudian saya tahu bahwa tidak ada satupun bengkel furniture di Papua punya alat selengkap karya misi Yesuit ini; dan bahwa semua alat itu harus dibawa dengan sebuah Landing Ship Tank, sebuah alat perang, seperti alegori sebuah perjuangan yang harus segera saya hadapi juga setelah menatap paroki kosong di Bomomani. Kompleks misi Bomomani, tepat di tengah pegunungan tengah Papua persis di antara distrik Kammu dan distrik Mapia, rupanya kumpulan bangunan kayu sederhana terserak di antara lahan kerikil dan tanah merah tempat rumput tinggi tumbuh subur di kebun dan sela-sela pekarangannya. Gereja kayunya berdiri sederhana dan belum terkesan tua dibanding usianya, sementara aula yang baru dibangun sudah menunjukkan tanda-tanda akan roboh, dinding di sebelah utara aula sudah miring keluar sekitar dua puluh derajat dan kuda-kuda atap sudah melengkung. Dua pondok bertingkat berdinding papan cincang juga sudah tak terawat, tampak seperti rumah hantu menambah suasana horor di lokasi yang dikeramatkan oleh penduduk setempat ini. Pastorannya kelihatan hendak dibuat baik tapi kurang persiapan. Kayu-kayunya masih basah sehingga semua bingkai melengkung membuat jendela dan pintu tidak bisa menutup rapat. Ketika melangkah di pastoran ini, jelas bahwa lantainya sangat rapuh, setiap membaringkan diri untuk tidur ada kekhawatiran lantai akan patah dan itu juga sudah terjadi. Saya tertawa, ternyata ada hunian pastor, yang jauh lebih parah dari pusat misi Yesuit di Nabire.
Seorang pastor, Vincent Suparman SCJ, adalah yang pertama menantang saya! Dengan lihai dia mulanya perlihatkan gereja Tiga Raja lama yang kuno dan mati gaya itu, baru kemudian menunjukkan kapela St. Fransiskus di susteran Charitas RSMM. “Ini baru gereja! Siapa dulu yang bangun… Freeport!” ujar Pater Vincent seolah-olah tidak ada orang lain yang bisa bikin barang bagus di Papua. Ini yang membuat saya sinis dalam hati, karena saya hitung-hitung, bangunan itu terlalu murah untuk perusahaan seperti Freeport. Diam-diam saya sudah rencanakan, “Nanti kamu lihat gereja baru di Bomomani…” bukankah ada banyak batu dan kayu yang bagus di Bomomani? Maka keyakinan itu semakin besar, saya seorang misionaris. Seorang misionaris akan temukan cara agar kabar gembira itu bisa sampai dan jiwa-jiwa dimenangkan bagi Allah. Freeport itu kecil dibandingkan back up yang mendukung saya, Tuhan Allah.
Akhirnya saya tidak lagi menuntut subsidi rutin dari Jakarta saat masa prapaskah pertama saya di pegunungan Mapiha, Papua (Maret 2005). Pakaian saya mulai kumal karena terbiasa mendorong-dorong drum bensin dan solar, yang laku keras di pedalaman. Saya seorang imam diosesan KAJ, dan kini misionaris di tanah Papua, menolak dimanjakan kemapanan karena Allah sudah manjakan saya dengan segala kecerdasan dan gagasan di kepala tolol ini untuk memperdaya modernitas bagi kepentingan umat. Saya melihat kegigihan Rm. Bas dan Rm.Yusuf yang tidak menyerah dengan keterbatasan situasi setempat, mereka bisa dan para Yesuit bertahun-tahun sudah mengajarkan pada saya semangat magis semper, selalu lebih, selalu mengatasi kemapanan…
“Ini Persis Seperti Yang Dahulu Kami Buat…”
Demikian ujar Br. Jan, OFM, yang datang meramaikan paskah 2009 di Bomomani. Saya sangat terkesan dengan bruder ini, pertama-tama karena dia pribadi yang sangat menyenangkan. Terlebih lagi, mempelajarinya sama seperti fosil hidup dari suatu nostalgia perintisan awal penyebaran Injil di wilayah pedalaman. Dari pribadinya saya menggali banyak hal terkait perjuangan misi membuka daerah terpencil ini. “Saya pukul anak-anak keras-keras karena saya sayang pada mereka,” katanya serius saat menjelaskan pola pendidikan asrama di Moanemani dahulu kala. Bruder Yan meyakinkan saya bahwa umat saya, orang Papua, bukan pemalas; mereka hanya terpisah ribuan tahun dengan peradaban. Misi Fransiskan, menafsirkan cerita Bruder Yan, adalah memberi kesempatan bagi umat untuk mengejar tahun-tahun yang hilang itu khususnya dengan pendidikan pertanian dan peternakan, dengan pengetahuan membaca agar umat bisa menemukan dunia yang lebih luas dari sekedar gunung gemunung di sekitar mereka. Lebih jauh lagi saya meneliti, para misionaris awal ini sudah memahami pokok permasalahan umat pribumi: pasar!

Br. Jan, OFM mengamati heran turbin air mikrohidro di kali Ihoai, sekitar tiga ratus meter ke sebelah barat kompleks misi, sungai itu sekaligus menjadi batas terjauh kompleks misi jika lokasi sekolah dasar YPPK, yayasan pendidikan milik Keuskupan Timika diperhitungkan sebagai wilayah misi juga. Pembangkit listrik tenaga air ini bukan kerja satu orang, ada akumulasi kerja keras dari sejumlah orang di Jakarta dan di Bomomani. Dari Jakarta, Budi Susanto, seorang bapak umat saya di Bojong adalah lulusan PIKA yang kemudian memproduksi mesin pengolahan kayu, Bp. Budi menyumbangkan bagian esensial yakni turbin. FX.Purwanto, paman saya menyumbangkan polly besar untuk percepatan putaran turbin, Om Pur tidak bosan sumbang ketika kiriman polly yang pertama ternyata tidak cocok untuk turbin dan mengirimkannya yang baru lagi, padahal harganya sama sekali tidak murah. Kemudian kabel-kabel, panjangnya mencapai 3 Km dalam berbagai ukuran, semuanya diusahakan oleh Om Pomo, kakak mama saya. FX. Soepomo ini meninggal persis tanggal 2 Nopember 2002, hari peringatan arwah, beliau didoakan dalam misa oleh Pastor Michael, yang sekarang bertugas di Bomomani sehingga semua kini terhubung.
Selain menyaksikan sebuah keajaiban listrik di gerbang belantara Mapia ini, Br.Jan juga melihat hal yang tidak biasa: para pemuda bina tani menyuburkan lahan rusak dengan kompos, sesuatu yang belum terjadi dijamannya, dan menanaminya dengan jagung, kedelai dan sayur mayur sebagai lingkaran kehidupan otonom kompleks misi. Jagung diolah menjadi makanan babi dan ayam potong, selanjutnya ayam potong dan anak-anak babi bisa di jual untuk membeli hancuran ikan asin, bahan olahan pakan babi dan ayam lalu keuntungannya dipakai untuk memenuhi kebutuhan lain bagi kegiatan misi. Demikian juga kedelai, digabungkan dengan hasil pembelian dari petani-petani lain, diolah menjadi tahu, yang diminati umat karena kurangnya pilihan lauk bergizi. Tahu, yang bentuknya mirip lemak babi, sering disebut sebagai babi Jawa karena umumnya diproduksi dan dikonsumsi orang jawa. Kelebihan sayur mayur seperti wortel, yang tak habis diserap segelintir pembeli lokal – sebab kemudian banyak umat ikutan menanamnya – dijual ke Nabire, Sr. Juliva Motulo SMSJ mengambil peran tersebut. Maka Br. Jan kembali senang melihat jaringan kerja Bomomani yang cukup rumit ditelusuri.
Sebenarnya kekaguman Br.Jan mesti mengarah pada saudari fransiskanesnya, Sr. Juliva Motulo SMSJ. Segala gagasan dari mulut bawelnya itulah yang kemudian menggerakkan saya melakukan hal-hal melelahkan melawan kemapanan pastoran Bomomani, yang setelah lima tahun menjadi tempat paling nyaman di pedalaman Papua. Dengan listrik 24 jam, saluran air jernih yang mengalir tiada henti untuk pabrik tahu disisihkan sebagian untuk pastoran, siaran televisi berbayar dari parabola telkomvision, jaringan transport yang mondar-mandir melengkapi kebutuhan hidup, komunikasi radio dan telepon satelit semuanya bisa membuat saya tenang-tenang saja menikmati hidup di Bomomani. Tapi kehadiran Sr.Juliva ini memang mengganggu kenyamanan saya. Minimal seminggu sekali dia miss call, memaksa saya telpon balik untuk tanyakan soal wortel, daun bawang atau tomat, yang akan dikirim ke Nabire atau melapor soal penjualannya atau tentang ayam, tentang babi-babi atau kemungkinan membuat misa di Legari sekalian membeli jagung di sana atau tentang apa saja gagasan yang ada di kepalanya diocehkannya ke telinga saya, seringkali ketika sebuah film bagus di putar di HBO, Cinemax atau Star Movie. Saya harus berkata ya, dan memberikan komitmen pelaksanaan untuk hentikan bawelnya.
Memang ocehan Sr. Juliva menjadi gagasan yang banyak saya ciptakan di Bomomani, sebagaiman gagasan saya juga menjadi banyak karya yang dimulainya di Nabire. Ocehannya soal ibu-ibu suku Mee yang berjualan di pasar Nabire, membuat gagasan menggiatkan pertanian sayur di Bomomani menjadi mungkin dibuat seperti juga gagasan saya tentang pengembangan ekonomi ibu-ibu di Nabire menjadi karya membuat kue dan menjahit dalam Rumah Bina Sosial yang dimulai Sr. Juliva bersama rekan sekomunitasnya. Jaringan yang selama ini membantu saya, akhirnya juga membantu Sr. Juliva sepe rti jaringan kerja yang dimilikinya dilibatkan juga membantu misi domestik mengembangkan contoh peternakan ayam potong di pedalaman untuk pertama kalinya.
rti jaringan kerja yang dimilikinya dilibatkan juga membantu misi domestik mengembangkan contoh peternakan ayam potong di pedalaman untuk pertama kalinya. Kemudian, Sr.Juliva berkenalan dengan seorang relawan FIDESCO, Cecile seorang sarjana pertanian asal Perancis yang cukup berhasil menghidupkan pembinaan pertanian dan peternakan di Lotta, Menado bersama dengan para relawan Perancis dan para pemuda-pemudi Menado. Perkenalan tersebut dibagikannya kepada saya sehingga akhirnya saya dan Cecile berbicara panjang tentang kemungkinan keterlibatan FIDESCO dalam misi domestik KAJ di Bomomani membangun sebuah Rumah Bina Tani. Maka kisah cinta itu semakin luas melampaui jarak yang terbayangkan bisa mudah dijangkau.
Satu Jiwa dalam Raga yang Berbeda
Kesaryanto, Pr menerima salib perutusannya sebagai misionaris domestik di Bomomani. Dia akan menemani Romi (panggilan akrab Rm. Michael), yang sudah sejak awal 2010 berkarya di Bomomani bersama saya. Dalam perjalanan ke puncak saat pertemuan unio tanggal 6 Juni 2011, saya bertanya “tesis lo tentang apa?” dan dia menjawab “diskursus Habermas dan Ratzinger” saya tersontak senang. Apakah ini suatu kebetulan lagi bahwa Romo Kes punya konsep sama memikirkan misi di Bomomani? Ketika saya dahulu membayangkan misi Bomomani menjadi kemilau dalam pergeseran cara pandang, suatu enlightment in paradigm shift, menjadi pioner dari perubahan budaya yang sementara ini masih dikagetkan ke arah yang acak oleh konsumerisme zaman modern lewat pemerintah yang bagi-bagi duit, para pendatang bak pedagang yang kejar keuntungan dan memperkuat ‘budayanya’ sendiri. Umat Bomomani ditarik paksa masuk peradaban maju sementara kegelapan menyelimuti mereka, kemana arah kemajuan itu? Apakah merdeka secara politik adalah kemajuan? Apakah mengumpulkan rupiah adalah kemajuan? Ataukah menjadi diri sendiri adalah kemajuan?
 Saya dan Romi merumuskan arah, menjadi diri sendiri sebagai petani yang katolik dan sejahtera dan mandiri sebagai hasil dari pewartaan Kabar Gembira dalam berbagai aspek dunia modern akan sekaligus membuat iman menjadi pemimpin umat mengembangkan budaya menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi. Suatu social deconstruction dari Habermas dan suatu true eucharist dari Gustavo Guttieres sekaligus. Bahasa tinggi ini pernyataannya sederhana, Romi ajar ibu-ibu Bomomani masak dan mengolah lauk dari sayur mayur yang ada, bersama-sama orang muda sesekali dia cari jamur di hutan pada musimnya sambil membuat percobaan jamur. Secara konsisten, Romi melahap tanaman tradisional mereka: nuta (ubi manis), nomo (keladi), sayur hitam, hatu (seperti ilalang), pego(seperti tebu, diambil bakal bunganya) dan iha bemu (sejenis jamur); dia membuat banyak percobaan masakan dengan bahan tersebut dan perkenalkan aneka sayuran baru: terong, bit, brokoli dan selada air. Hobinya menanam aglonema yang mahal dialihkan menanam buncis, wortel dan kacang panjang sambil menghibur diri membudidayakan anggrek langka yang diambilnya dari puncak perbukitan di sekitar Bomomani. Walaupun pastoran belum dipugar seperti gereja baru dan asrama yang keduanya kelihatan gagah, Romi sudah merapikannya sedemikan hingga membuatnya sudah tampak lebih baik dari losmen melati di pinggiran Jakarta. Umat yang sudah bertahun-tahun hanya bisa menanam dan menjual biji segar kopi kini mulai bisa minum kopi hasil buatan mereka sendiri dengan alat sederhana yang ada di dapur mereka.
Saya dan Romi merumuskan arah, menjadi diri sendiri sebagai petani yang katolik dan sejahtera dan mandiri sebagai hasil dari pewartaan Kabar Gembira dalam berbagai aspek dunia modern akan sekaligus membuat iman menjadi pemimpin umat mengembangkan budaya menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi. Suatu social deconstruction dari Habermas dan suatu true eucharist dari Gustavo Guttieres sekaligus. Bahasa tinggi ini pernyataannya sederhana, Romi ajar ibu-ibu Bomomani masak dan mengolah lauk dari sayur mayur yang ada, bersama-sama orang muda sesekali dia cari jamur di hutan pada musimnya sambil membuat percobaan jamur. Secara konsisten, Romi melahap tanaman tradisional mereka: nuta (ubi manis), nomo (keladi), sayur hitam, hatu (seperti ilalang), pego(seperti tebu, diambil bakal bunganya) dan iha bemu (sejenis jamur); dia membuat banyak percobaan masakan dengan bahan tersebut dan perkenalkan aneka sayuran baru: terong, bit, brokoli dan selada air. Hobinya menanam aglonema yang mahal dialihkan menanam buncis, wortel dan kacang panjang sambil menghibur diri membudidayakan anggrek langka yang diambilnya dari puncak perbukitan di sekitar Bomomani. Walaupun pastoran belum dipugar seperti gereja baru dan asrama yang keduanya kelihatan gagah, Romi sudah merapikannya sedemikan hingga membuatnya sudah tampak lebih baik dari losmen melati di pinggiran Jakarta. Umat yang sudah bertahun-tahun hanya bisa menanam dan menjual biji segar kopi kini mulai bisa minum kopi hasil buatan mereka sendiri dengan alat sederhana yang ada di dapur mereka.Akhirnya untuk kedua rekan misionaris, selamat mengkaryakan dunia gagasan dalam misi domestik KAJ di Bomomani. Romo Michael dan Romo Kes, tunjukan bahwa kita HAMBA, kita mengabdi dengan penuh kerendahan hati sebagai gembala yang baik. Hangat dalam perjumpaan dengan umat adalah trademark yang terus kita tampilkan, gaul istilah biasa yang akan kita dengar di Jakarta sekaligus bisa di-andal-kan untuk melakukan tugas-tugas yang jelas tidak pernah mudah, misioner karena siap diutus kemana saja dengan semangat lepas bebas dari apapun yang memikat dan mengikat hati kita, tentu saja bahagia sebagai imam adalah hal penting bagi kekekalan panggilan sampai mati dan jangan lupa ikut andil dalam aneka kepentingan keuskupan tempat kita mengabdi, karya kita di Bomomani bisa meluas membawa kebaikan bagi aneka karya Keuskupan Timika, khususnya untuk paroki-paroki yang berdekatan. ‘…kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?’ (Mzm 56:5) enakidabi