APA SEBENARNYA TUGAS GEREJA DI PAPUA ?
(Sebuah Refleksi Pastoral)
By Santon Tekege
By Santon Tekege
“SERUAN orang Papua bagi keadilan dan kebenaran jatuh pada telinga-telinga tuli”, begitulah komentar Mgr. Desmond Tutu, uskup Agung Afrika dalam sebuah seruan yang diajukannya dalam rangka menyikapi penindasan terhadap orang Papua dan mendorong perjuangan pembebasan nasional Papua kepada Sekjen PBB. Ungkapan ini menujukan bahwa sudah sekian lama orang Papua berjuang untuk bebas dari penindasan, namun segala daya upaya yang dilakukan oleh orang Papua bagaikan menabur garam di Lautan. Jeritan orang Papua kurang direspons oleh manusia di bumi. Suara orang Papua tidak diindahkan oleh pelaku distorsi sejarah Papua, yakni Indonesia, Belanda dan Amerika Serikat.
Uskup Desmond Tutu adalah salah seorang uskup di benua lain yang menyuarakan suara kenabian bagi pembebasan orang Papua. Kalaupun beliau berada di belahan dunia lain, namun beliau mempunyai telinga sehinga mendengarkan dan mempertanyakan pelaksanaan PEPERA yang direkayasa dan dimanipulasi di bawah tekanan militer Indonesia.
“Dengan keprihatinan yang mendalam, saya telah mempelajari peranan PBB dalam pengambil-alihan Papua Barat oleh Indonesia dan Penentuan Pendapat Rakyat yang kelabu. Sebagai pengganti refrendumnya yang sebenarnya, setiap orang dewasa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan untuk memberikan suara yang rahasia tentang apakah mereka ingin menjadi bagian dari Indonesia atau tidak, di mana hanya lebih dari 1.000 orang yang dipilih dan dipaksa untuk menyatakan bagian Indonesia di depan umum dalam suasana ketakutan dan tekanan”.
Beliau mempertanyakan pelaksanaan PEPERA dan menyerukan kepada PBB untuk mengadakan peninjauan kembali terhadap pelaksanaan PEPERA. “Saya senang akan menambahkan suara saya pada seruan Internasional yang semakin meningkat kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk memeriksa peninjauan kembali sikap PBB dalam hubungan dengan PEPERA 1969 yang cacat itu”.
Beliau juga tidak hanya sekali menyerukan kepada PBB, tetapi sebagai pemerhati masalah kemanusiaan dan juga tokoh agama mendukung perjuangan Papua melalui doa dan menyampaikan seruan moral sejauh itu dibutuhkan oleh orang Papua dalam perjuangan pembebasan. “Saya akan mengingat rakyat Papua dalam doa-doa saya, dan saya akan senang menyampaikan kerinduan dan dukungan moral saya yang besar bagi mereka pada waktu yang mereka butuhkan”.
Barangkali orang lain beranggapan bahwa seruan dan pernyataan uskup Desmond Tutu adalah berbicara politik praktis. Namun, bagi uskup Desmond Tutu adalah masuk akal dan rasional, bukan politik praktis. Menurut uskup Desmond Tutu adalah merupakan suatu keharusan bagi pemimpin agama untuk menyuarakan suara kenabian karena soal kemanusiaan Papua yang juga sebagai ciptaan Tuhan yang sedang menuju ke ambang kepunahan etnis. “Rakyat Papua telah disangkal hak-hak dasar mereka, termasuk hak menentukan sendiri… Sekitar 100.000 orang telah meninggal di Papua sejak Indonesia mengambil alih wilayah ini pada 1963”. Ketika membaca atau mendengar seruan Mgr. Desmond Tutu, barangkali pemimpin agama atau orang lain beranggapan bahwa beliau mengajukan pernyataan kepada PBB hanya karena orang Papua adalah berkulit hitam yang sama dengannya. Anggapan seperti ini memang benar bahwa uskup Desmund Tutu adalah orang berkulit hitam, akan tetapi beliau berbicara tentang kemanusiaan. Masalah kemanusiaan tidak dibatasi oleh agama, suku, ras dan golongan. Berbicara tentang martabat manusia menembus segala dimensi perbedaan.
Uskup Desmond Tutu adalah salah seorang uskup di benua lain yang menyuarakan suara kenabian bagi pembebasan orang Papua. Kalaupun beliau berada di belahan dunia lain, namun beliau mempunyai telinga sehinga mendengarkan dan mempertanyakan pelaksanaan PEPERA yang direkayasa dan dimanipulasi di bawah tekanan militer Indonesia.
“Dengan keprihatinan yang mendalam, saya telah mempelajari peranan PBB dalam pengambil-alihan Papua Barat oleh Indonesia dan Penentuan Pendapat Rakyat yang kelabu. Sebagai pengganti refrendumnya yang sebenarnya, setiap orang dewasa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan untuk memberikan suara yang rahasia tentang apakah mereka ingin menjadi bagian dari Indonesia atau tidak, di mana hanya lebih dari 1.000 orang yang dipilih dan dipaksa untuk menyatakan bagian Indonesia di depan umum dalam suasana ketakutan dan tekanan”.
Beliau mempertanyakan pelaksanaan PEPERA dan menyerukan kepada PBB untuk mengadakan peninjauan kembali terhadap pelaksanaan PEPERA. “Saya senang akan menambahkan suara saya pada seruan Internasional yang semakin meningkat kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk memeriksa peninjauan kembali sikap PBB dalam hubungan dengan PEPERA 1969 yang cacat itu”.
Beliau juga tidak hanya sekali menyerukan kepada PBB, tetapi sebagai pemerhati masalah kemanusiaan dan juga tokoh agama mendukung perjuangan Papua melalui doa dan menyampaikan seruan moral sejauh itu dibutuhkan oleh orang Papua dalam perjuangan pembebasan. “Saya akan mengingat rakyat Papua dalam doa-doa saya, dan saya akan senang menyampaikan kerinduan dan dukungan moral saya yang besar bagi mereka pada waktu yang mereka butuhkan”.
Barangkali orang lain beranggapan bahwa seruan dan pernyataan uskup Desmond Tutu adalah berbicara politik praktis. Namun, bagi uskup Desmond Tutu adalah masuk akal dan rasional, bukan politik praktis. Menurut uskup Desmond Tutu adalah merupakan suatu keharusan bagi pemimpin agama untuk menyuarakan suara kenabian karena soal kemanusiaan Papua yang juga sebagai ciptaan Tuhan yang sedang menuju ke ambang kepunahan etnis. “Rakyat Papua telah disangkal hak-hak dasar mereka, termasuk hak menentukan sendiri… Sekitar 100.000 orang telah meninggal di Papua sejak Indonesia mengambil alih wilayah ini pada 1963”. Ketika membaca atau mendengar seruan Mgr. Desmond Tutu, barangkali pemimpin agama atau orang lain beranggapan bahwa beliau mengajukan pernyataan kepada PBB hanya karena orang Papua adalah berkulit hitam yang sama dengannya. Anggapan seperti ini memang benar bahwa uskup Desmund Tutu adalah orang berkulit hitam, akan tetapi beliau berbicara tentang kemanusiaan. Masalah kemanusiaan tidak dibatasi oleh agama, suku, ras dan golongan. Berbicara tentang martabat manusia menembus segala dimensi perbedaan.
Masalah kemanusiaan bukanlah masalah golongan atau rasisme dan sebagainya, melainkan merupakan masalah semua manusia yang berada di planet ini (bumi). Oleh karena itu, setiap manusia harus melihat masalah kemanusian sebagai masalah universal yang tidak dibatasi oleh ras, suku, agama dan golongan. Demikian pula penegakan martabat manusia Papua, berarti bukanlah berbicara rasisme, atau agamaisme, dan seterusnya, melainkan berbicara kemanusiaan Papua sebagai ciptaan Tuhan yang sama dengan manusia lain, maka mereka harus dihargai eksistensinya sebagai manusia.
Selain Uskup Desmon Tutu, ada pula uskup dan beberapa pendeta di wilayah Melanesia juga menyerukan suara kenabian. Salah seorang uskup Katolik Meuborne Australia, Mgr. Hilton Deaken memimpin sebuah Perayaan Eukumene untuk mendoakan perjuangan pembebasan orang Papua. Dalam perayaan tersebut mereka menyerukan: 1) segenap rumpun bangsa Melanesia di seluruh dunia mendukung dan membantu perjuangan pembebasan orang Papua; 2) Tinjau kembali PEPERA 1969; 3) Perlunya DIALOG antara Indonesia dan Papua itu kalau mendesak oleh orang Papua dan orang asli Papua di seluruh wilayah Papua.
“Menghimbau segenap rumpun bangsa Melanesia di seluruh dunia agar lebih giat membantu dalam perjuangan kebebasan dari penindasan dan ketidakadilan di Papua di Indonesia. Seluruh rumpun bangsa Melanesia yang tersebar di seluruh dunia perlu mendesak PBB agar mempertimbangkan kembali Penentuan Pendapat Rakyat atau PEPERA tahun 1969, yang dijadikan landasan resmi untuk menyatukan Irian ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Tetapi juga pelanggaran HAM, menindas budaya dan identitas sebagai orang asli Papua, masalah perampasan sumber daya alam, masalah kesehatan dan pendidikan yang terpuruk di tanah Papua bahkan illegal logging.
Para tokoh Gereja ini menyadari bahwa perjuangan orang Papua bukanlah kekecewaan atas kesejahteraan ekonomi semata, melainkan segala permasalahan kemanusiaan yang buat oleh penguasa Indonesia. Untuk itu, hal pertama yang harus dilaksanakan adalah tinjau kembali PEPERA. Karena menurut mereka PEPERA dilakukan di bawah tekanan militer dan tidak demokratis. Oleh sebab itu, meninjau kembali pelaksanaan PEPERA merupakan hal penting yang harus diperhatikan dan ditinjau kembali. Mengapa? Hanya karena penafsiran terhadap distorsi sejarah yang keliru mengakibatkan dengan orang Papua dibantai satu persatu.
Seruan yang sama juga datang dari seorang mantan uskup Sorong-Monokwari, Mgr. Vandiepen yang berada di Belanda. Dalam sebuah perayaan khusus bagi perjuangan pembebasan orang Papua, beliau menyerukan dua hal, yakni 1) perjuangan orang Papua adalah perjuangan ketidak-puasan mereka terhadap pelaksanaan PEPERA yang dinilai penuh rekayasa dan pemanipulasian serta tidak demokratis, maka diserukan kepada setiap orang yang beretikat baik perlu mendukung perjuangan orang Papua; 2) menyerukan kepada semua umat Allah bahwa segera merapatkan barisan dan mendukung perjuangan orang Papua karena merekalah juga manusia sama seperti kita di bumi ini.
Seruan Mgr. Vandiepen di atas dilatar-belakangi oleh pengalamannya ketika beliau bersama dengan umatnya di Papua. Beliau telah melihat dan mendengar serta merasakan sendiri betapa pahit dan sadisnya penindasan yang dilakukan terhadap umatnya di Papua. Ia merasa bahwa sewaktu masa usia tuanya, ia harus berbuat sesuatu bagi umatnya yakni menyerukan dan menyatakan sesuatu yang benar kepada masyarakat Internasional agar menyelesaikan masalah Papua dengan menyentuh akar persoalan yang sudah lama terkubur. Barangkali pengalaman pahit bersama dengan umatnya mendorongnya untuk menyerukan kepada dunia sebagai ujud keterlibatannya dalam pembebasan nasional bangsa Papua.
Seruan Mgr. Vandiepen salah satu mantan uskup yang pernah bertugas di Papua menyentuh akar persoalan (distorsi sejarah) yang melahirkan dua masalah baru, yakni masalah HAM dan segala masalah kemanusiaan di Papua. Mgr. Vandiepen merasa bahwa distorsi sejarahlah yang mengakibatkan hak hidup orang Papua terancam. Oleh sebab itu, ia dengan berani menyerukan dan menyatakan kepada dunia bahwa perjuangan orang Papua adalah berhubungan dengan distorsi sejarah (PEPERA) yang dilakukan di bawah tekanan militer Indonesia. Beliaulah mantan uskup pertama yang pernah mengalami dan melihat penindasan terhadap umatnya di Papua, maka ia tidak tanggung-tanggung dan menyatakan kepada masyarakat Internasional bahwa dasar perjuangan orang Papua adalah ketidakpuasan terhadap pelaksanaan PEPERA.
Seruan point kedua menujukan bahwa pentingnya keterlibatan semua orang sebagai ungkapan solidaritas terhadap orang di Papua yang telah dan sedang mengalami penindasan dan pemusnahan, baik terselubung maupun juga terangan-terangan. Beliau menyadari bahwa dukungan kita semua di bumi, sangatlah dibutuhkan untuk mendorong perjuangan orang Papua. Beliau menyerukan kepada semua umat manusia, tanpa memandang ras, suku, agama dan golongan yang beretikat baik segeralah mengambil sikap untuk mendukung perjuangan pembebasan orang Papua, karena perjuangan orang Papua memiliki dasar yang jelas, yakni distorsi sejarah yang mengakibatkan lahirlah dua masalah baru, yakni pelanggaran HAM dan juga segala masalah dalam berbagai aspek sosial. Hanya karena distorsi sejarah membawa malapetaka bagi eksisntesi orang Papua. Jika pemerintah Indonesia beretikat baik dengan orang Papua, maka hal pertama yang harus dibicarakan adalah meninjau dan meluruskan sejarah politik orang Papua.
Selain beberapa uskup dan pendeta di atas, masalah Papua dibicarakan dalam Dewan Gereja-Gereja Amerika Serikat. Kini giliran Dewan Gereja Amerika Serikat untuk menyuarakan suara kenabian mereka atas perjuangan orang Papua menuju pembebasan. Barangkali pemimpin Gereja-gereja di Amerika Serikat merasa bahwa mereka perlu memberikan dukungan moril terhadap perjuangan pembebasan orang Papua. Oleh sebab itu, masalah Papua menjadi salah satu masalah yang harus diperbicangkan dalam dewan gereja Amerika Serikat demi mencari solusi yang terbaik bagi penanganan dan penyelesaian masalah Papua. Lalu bagaimana dengan uskup-uskup dan pendeta-pendeta yang ada di benua Asia. Kita tidak pergi jauh-jauh, tetapi kita mengintropeksi diri di Indonesia.
Bagaimana tanggapan pendeta dan uskup-uskup di Indonesia terhadap jeritan dan harapan umatnya yang sedang dalam penindasan dan penderitaan? Nampaknya para pemimpin Gereja tidak serius dalam penanganan dan penyelesaian masalah Papua. Pihak Gereja menyembunyikan akar masalah, yakni distorsi sejarah dan menyembunyikan penderitaan serta penindasan umatnya bahkan masalah kemnusiaan pun disembunyikan.
Memang benarlah apa yang dikatakan oleh uskup Desmond Tutu: “Seruan orang Papua bagi keadilan dan kebenaran jatuh pada telinga-telinga”. Mengapa? Pemimpin-pemimpin agama, khususnya pimimpin Gereja di Indonesia, lebih khusus lagi pemimpin Gereja di Papua - sekalipun tidak semua - bungkam seribu bahasa. Barangkali Gereja di Papua berpikir bahwa manusia yang berada dalam kemelut penidasan, bukanlah umatnya, atau belum saatnya Gereja berbicara karena aktor-aktor penindasan terhadap orang Papua adalah orang Indonesia di mana para petugas Gereja sendiri adalah mayoritas orang Indonesia, maka penindasan terhadap umatnya dibiarkan. Atau berpikir bahwa ketika manusia tertindas, semakin minoritas baruluh bangkit dan terpanggil untuk menyuarakan suara kenabian; atau dunia Intrenasional menyikapi situasi di Papua, barulah Gereja di Papua bangkit menyatakan yang benar demi menghilangkan imit tentang keapatisan Gereja dan menyatakan kepada orang lain bahwa Gereja di Papua juga sedang menyuarakan suara kenabian. Atau juga barangkali pemimpin Gereja menyadari bahwa penindasan yang terjadi di Papua tidak begitu sadis dan hebat dibanding penindasan yang dialami oleh massa rakyat di Amerika Latin. Jika pandangan-pandangan inilah yang tertancap kuat dalam sanubari petugas Gereja–sekali-pun tidak semua, maka boleh dikatakan pemimpin Gereja membiarkan penindasan terhadap umatnya.
Penulis menyadari akan keberadaan Gereja. Gereja amat berhati-hati untuk terlibat dalam politik praktis. Untuk para hierarkis Gereja katolik dilarang keras terlibat dalam politik praktis. Hal ini telah ditegaskan dalam Hukum Kanonik sehingga Gereja diikat dengan hukum tersebut. Kebebasan para hierarkis untuk menyatakan kebenaran terkadang dibatasi oleh hukum Gereja dan juga hukum positif (buatan manusia). Tugas Gereja untuk memihak kepada mereka yang tertindas, termiskin dan termarginalisasi seperti umat dan jemaatnya di Papua yang mengalami penindasan dari sejak tahun 1960-an hingga kini tahun 2011, terkadang diabaikan. Tugas Gereja untuk mewartakan kebenaran dan keadilan terkadang tidak sesuai dengan konteks.
Mengapa Gereja bungkam seribu bahasa untuk menyatakan yang benar tentang distorsi sejarah – PEPERA - yang direkayasa, dimanipulasi, tidak demokratis dan dilakukan di bawah tekanan represif militer Indonesia kepada penguasa yang menyembunyikan kesalahannya? Gereja menyembunyikan kesalahan negara, berarti secara tidak langsung Gereja menindas umatnya. Sikap apatisme Gereja dalam menyembunyikan kesalahan distorsi sejarah yakni pemanipulasian PEPERA adalah merupakan pengakuan dan juga mempertahankan status neo-kolonialisme terhadap orang Papua..
Tugas Gereja adalah menegakan kebenaran dan keadilan. Gereja bukan hanya mewartakan kebenaran yang terdapat dalam Alkitab, tetapi juga menyikapi dan menegakkan kebenaran dan keadilan dalam situasi kongkrit yang dialami oleh umatnya. Petugas Gereja tidak hanya berkata-kata, tetapi perkataannya harus diwujudkan dalam tindakan nyata/aksi sosial. Hal ini dikatakan demikian karena situasi di Papua dituntut sikap dan tindakan nyata dari para petugas Gereja di Papua untuk bangkit dan menyuarakan suara kenabian dan kebenaran serta keadilan. Gereja harus berpihak kepada umat yang tertindas, termarginalisasi dan membebaskan mereka dari tirani adat, pemerintahan dan agama. Tirani penindasan semakin meningkat di Papua, maka petugas Gereja sebagai penerus, pengemban visi dan misi Yesus harus mengangkat umatnya yang berada dalam tirani penindasan dan dosa struktural yang membelenggu umatnya. Gereja harus berpihak kepada umatnya yang tertindas dan membawa serta menyatakan keperihatinan-Nya, sama seperti Yesus membawa keprihatinan Allah. “Ia setia kawan dengan kemalangan manusia. Berpihak kepada yang lemah dan menderita, Yesus hidup berjuang untuk mereka.” Ungkapan keperpihakan Yesus ditegaskan dalam Injil Lukas, 10:34, yang berbunyi: “tergeraklah hati-Nya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut lukanya”. Yesus adalah soko guru bagi umat Kristiani. Yesus selama hidup-Nya menekankan betapa pentingnya kasih. Kasih diwujudnyatakan dalam perbuatan.
“Rencana kerja Yesus tidak berhenti pada rencana bagus, tetapi dengan setia mewujudkan di dalam seluruh sikap dan perilaku hidup Yesus. Karena itu kepada Yohanes Pemandi Yesus menyatakan kesetiaan hidup itu, dan mengajak setiap orang menemukan kebahagiaan hidup karena memilih dan berpihak pada korban.”
Ungkapan di atas ditegaskan dalam Lukas, 7: 22 : “Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar: orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku”. Ayat-ayat tersebut merupakan sikap dan perbuatan Yesus, di mana Ia memihak kepada umat-Nya yang menderita. Ia tidak hanya berkata-kata, akan tetapi diwujudnyatakan dalam perbuatan nyata (aksi sosial).
Jika Gereja benar-benar melanjutkan visi dan misi Yesus, maka sudah saatnya Gereja terdorong dan tampil sebagai nabi pada jaman kini untuk memaklumkan kebenaran dan keadilan di Papua. Gereja jangan membiarkan umatnya berada dalam belenggu penindasan, tetapi mengangkat dan membebaskan umatnya yang dipercayakan Allah untuk melayani dan membebaskan mereka dari belenggu penindasan. Dalam hal ini, petugas Gereja di Papua kiranya harus belajar dari pengalaman uskup Timor Leste, uskup dan pastor-pastor di Amerika Latin. Ketika umatnya berada di bawah kemelut penindasan, mereka tampil dan menyuarakan suara kebanarn dan keadilan. Mereka bergabung dengan umatnya menentang para tirani-tirani penguasa yang menindas umatnya, bahkan sampai mereka mengangkat senjata menghadapi tirani penguasa.
Uskup Belo misalnya, beliau terdorong dan memiliki beban moril untuk memperjuangkan pembebasan umatnya untuk keluar dari cengkeraman penguasa yang tidak biadab. Demikian pula uskup-uskup di Amerika Latin mengangkat senjata hanya karena merasa terdorong untuk membebaskan umatnya yang ditindas oleh penguasa. Mereka mengangkat senjata hanya karena membela harkat dan martabat manusia yang kala itu berada dalam ancaman. Keprihatinan mereka terhadap umat tertindas itulah yang mendorong mereka untuk melawan tirani penindasan.
Bagaimana dengan petugas Gereja di Papua? Kiranya Gereja tidur lelap. Barangkali Gereja bagaikan tidak mempunyai kuping sehingga Gereja kurang mendengarkan penderitaan umatnya; barangkali Gereja bagaikan tidak mempunyai mata sehingga tidak melihat penderitaan umatnya; barangkali Gereja bagaikan tidak mempunyai perasaan sehingga Gereja kurang merasakan penderitaan umatnya; barangkali Gereja tidak mempunyai akal budi, karena Gereja kurang memikirkan dan merenungkan nasib malang yang menimpa umatnya. Singkatnya, barangkali Gereja tidak prihatin dengan apa yang dialami oleh umatnya di Papua. Semestinya, Gereja sadar akan penindasan yang dialami oleh umatnya. Sebetulnya Gereja ada di Papua untuk menjawab kebutuhan umat setempat. Gereja bukan ada hanya untuk melayani sakramen-sakramen di Gereja saja, melainkan lebih dari itu. Salah satunya adalah mendengar jeritan dan tangisan, melihat penderitaan umatnya, merasakan dan memikirkan jalan keluar demi pembebasan umatnya. Namun, entalah Gereja di Papua menciptakan budaya bisu dan apatis dengan realita umatnya. Kiranya benar apa yang dikatakan oleh J.H. Padmoharjono, SJ: “Keprihatian kepada yang lemah, yang menderita menjadi korban dosa dari sesama yang kuat, pandai dan berkuasa tidak didengar dan ditanggapi oleh manusia”. Petugas Gereja di Papua –sekalipun tidak semua-masuk dalam kategori ini, karena belum ada sikap yang nyata oleh Gereja dalam memerangi penindasan dalam terang Injil di Papua.
Orang Papua sebagai korban penindasan mengidungkan kidung ratapan dan tangisan, teriakan umatnya membung-bung dan tak henti-hentiknya menyuarakan kepedihannya, namun jeritan orang Papua jatuh di telinga-telinga tuli. Juga jatuh di mata buta seperti ikan cakalang di Pasar Youtefa Jayapura (matanya terbuka lebar tetapi tidak melihhatnya)
“Dari tanah, dari darah atau penderitaan saudara sesama manusia menjadi korban tindakan berdosa, - karena mereka lemah dan tak berdaya – mereka menjerit ke Surga kepada Tuhan minta keadilan. Hingga saat ini, manusia masih bersikap sama: tidak peduli akan keprihatinan Allah”.
Inilah ungkapan keprihatian seorang pastor yang mengikuti penderitaan umatnya di Indonesia. Di manakah Engkau “Gereja” di Papua??? Apa sebenarnya tugas Gerjeja di Papua? Untuk apa Gereja ada di Papua? Apakah Engkau “Gereja” ada di Papua hanya untuk mewartakan Injil dan hanya sibuk melayani sakramen-sakramen di gereja? Begitukah visi dan misi Yesus? Kiranya hal ini kita refleksikan bersama.
Ada juga sikap lain yang dilakukan oleh Gereja - sekalipun tidak semua - yang ujung-ujungnya memojokkan dan merugikan umatnya. Apa sikap Gereja tersebut? Gereja menjadi kaki tangan dari Pemerintah untuk memaksakan paket politik pemerintah, misalnya Otsus, MRP dan segala perusahan termasuk (MIFEE dan Kelapa Sawit) yang di dalamnya terdapat racun yang mematikan bagi umatnya di Papua. Petugas Gereja menjadi penyambung dan pemaksa kebijakan Pemerintah Pusat untuk di terapkan di Papua. Hal ini nampak melalui sikap dan perilaku Gereja –sekalipun bukan semua. Contohnya, ketika penulis menghadiri diskusi yang dihadiri para wartawan, pimpinan Gereja dan mahasiswa, salah seorang pemimpin Gereja di Papua mengatakan dengan tegas: “MRP segera dibentuk agar orang Papua merasakan Otsus”. Ungkapan ini menunjukkan bahwa Gereja memaksakan umatnya menerima Otsus dan MRP untuk tetap diterapkan di Papua, pada hal umat di Papua telah menolak Otsus. Sikap seperti ini tidak jauh beda dengan sikap Pemerintah Propinsi Papua dan Pusat untuk memaksakan sesuatu yang tidak dikehendaki umatnya untuk diterapkan di Papua. Walaupun umatnya menolak, namun pemimpin Gereja menjadi mitra kerja Pemerintah Indonesia untuk menjalankan Otsus di Papua.
Kami sebagai aktivis pro-demokrasi, pro kebenaran dan keadilan serta pro-pembebasan rakyat Papua barat dapat kami katakan bahwa Gereja menjadi salah aktor dalam menindas umat. Gereja menjadi salah satu wadah untuk melunakkan hati umatnya dengan pewartaan-pewartaan yang sebenarnya tidak kena konteks dengan situasi di Papua. Mereka mendorong dan mendukung kebijakan Pemerintah untuk tetap diterapkan di Papua, sekalipun kebijakan tersebut mendatangkan malapetaka bagi umatnya.
Selama ini Gereja kurang peka terhadap jeritan dan harapan umatnya yang ditindas oleh penguasa Indonesia. Gereja lebih mengutamakan pelayanan Ibadah atau Sakramen-sakramen dari pada mendahulukan keadilan dan perdamaian. Hal ini berarti tidak sejalan dengan amanah Yesus Kristus, sogo guru umat Kristen: “…tinggalkanlah persembahan di depan Mesbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu” (Mat. 5:24). Apakah Gereja peduli dengan realitas penindasan yang dialami oleh umatnya? Apakah masih ada waktu bagi Gereja untuk menyuarakan realitas penindasan yang dialami oleh umatnya?
Gereja di Papua belum terlambat. Gereja masih ada waktu untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan serta menyatakan yang benar kepada Indonesia. Massa rakyat Papua menantikan pemimpin Gereja di Indonesia, lebih khusus petugas Gereja yang bertugas di Papua untuk tidak menyembunyikan kebenaran dan keadilan, akan tetapi menyatakan secara jujur tentang kebenaran dan keadilan yang diabaikan oleh Pemerintah dan mendorong Pemerintah untuk mendengar dan melakukan solusi terbaik yang dikehendaki oleh umatnya. Minimalnya mendesak Pemerintah untuk membuka dialog damai dengan umatnya di Papua.
Gereja harus beretikat baik bagi umatnya tertindas di Papua. Gereja sudah saatnya bangkit untuk membebaskan umatnya dari kemelut penindasan. Juga Gereja sebaiknya jangan menjadi kaki tangan Pemerintah untuk memaksakan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak umatnya, akan tetapi Gereja berusaha mencari solusi untuk membebaskan umatnya keluar dari kemelut penindasan dan ketidakadilan..
Tak dapat disangkal bahwa ada pemimpin Gereja tertentu yang melakukan tindakan perlawanan terhadap tirani-tirani penindasan. Patutlah dan doakanlah bagi mereka yang selama ini menyuarakan suara kenabian, dan memihak kepada rakyat tertindas, antara lain bisa dihiung dengan jari dan lain sebagainya. Mereka adalah gembala umat yang sudah dan sedang mengikuti, mengalami dan merasakan betapa pahitnya penindasan yang dilakukan oleh tirani-tirani penguasa terhadap umatnya. Mereka merasa bahwa menyelamatkan jiwa-jiwa adalah tugas Gereja dan mereka dipilih dan dipanggil oleh Allah untuk menyuarakan suara kenabian dan menegakkan kebenaran serta keadilan di Papua Barat. Bagi mereka memihak kepada rakyat tertindas adalah tugas yang paling mulia dan untuk itulah mereka diutus. Tindakan perlawanan beberapa pemimpin Gereja di Papua adalah merupakan tindakan penyelamatan dan pembebasan bagi umat tertindas. Tindakan dalam proses pembebasan ini demi kemuliaan sesama dan lebih-lebih demi kemuliaan nama Tuhan.
Mampukah Gereja di Papua membebaskan umatnya yang berada dalam ancaman kepunahan etnis? Mampukah Gereja melanjutkan visi dan misi Yesus Kristus serta mendaratkan visi dan misi dalam konteks penderitaan di Papua? Ataukah Gereja di Papua menciptakan visi dan misi baru sehingga mengabaikan tugas yang sebenarnya, dan menindas umatnya? Kapan Gereja di Papua akan bangkit dan membebaskan umatnya dari lumpur duka nestapa?
Daftar Pustaka :
1. Padmoharjosono, J.H. SJ. 2002. Supleman APP; Kerangka Dasar Rekonsilisasi:
Upaya Hhidup Damai, Rukun dan Bersatu. Jakarta: Komisi PSE KWI.
2. Imbiri, Leonard. 2005. Masalah Papua Dalam Pandangan Tokoh Dunia. Jayapura.
3. Tebay, Neles, Pr. Dialog Jakarta-Papua (sebuah perspektif Papua), SKP Jayapura 2009

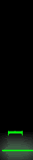

0 komentar:
Posting Komentar