Persoalan Papua telah lama dibingkai dalam warna kekerasan yang begitu dominan, sementara realitas persoalan begitu kompleks dan membutuhkan pendekatan khusus. Presiden Jokowi menekankan pentingnya pendekatan dialog, sementara masih saja kita mendengar ada persoalan kekerasan di Bumi Cendrawasih ini. Seperti apa sebenarnya keadaan di sana? Bagaimana pemerintahan Jokowi memandang persoalan ini?
Terkait ini, tanggal 14 Desember lalu Berdikari Online (BO) secara khusus melakukan wawancara dengan Jaleswari Pramodhawardani (JP), Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan, di Kantor Staf Presiden, Bina Graha, Jakarta. Kurang lebih baru satu tahun terakhir, Mbak Dani, demikian biasa disapa, berkecimpung dalam isu Papua sesuai bidang tugasnya. Meski demikian ia cukup fasih menerangkan persoalan Papua dalam berbagai aspek dan memberikan tawaran solusi yang sedang diupayakan.
Sampai sekarang ini banyak persoalan Papua yang muncul di permukaan dan kemudian menjadi perhatian di nasional bahkan sudah ada upaya menginternasionalisasi masalah Papua ini. Yang paling sering menjadi perhatian adalah persoalan pelanggaran HAM. Nah, pemerintahan Jokowi menyampaikan akan lebih menggunakan pendekatan dialog untuk menyelesaikan masalah Papua ini. Sejauh mana pendekatan ini telah berjalan?
JP: Persoalan Papua ini kan bukan baru, selalu dibicarakan dan mencoba dicarikan solusinya di era semua presiden yang memerintah, dari presiden Soekarno hingga presiden SBY , bukan mendadak pada pemerintahan presiden Jokowi saja. Persoalan di Papua itu sangat kompleks. Ada distrust yang sangat kuat, antara Jakarta ke Papua, dan Papua ke Jakarta. Dan ini memang tidak mudah diperdamaikan hanya karena rejim ini berganti.
Yang tertinggal dari ingatan kolektif sebagian kawan-kawan di Papua tentang Indonesia atau Jakarta tentang unsur kekerasannya, pelanggaran HAM, dan represi aparat keamanannya. Media nasional dan asing memberitakan itu semua. Hal ini menenggelamkan berita baik lainnya yang sebenarnya juga banyak dilakukan pemerintah pusat untuk membangun Papua. Jarang sekali diberitakan bagaimana dana otonomi khusus itu mewujud dalam bentuk pembangunan yang bermanfaat di Papua. Yang ada justru informasi dana otsus yang begitu besar itu tidak memiliki dampak signifikan bagi rakyat Papua, walaupun otsus (otonomi khusus_red) sudah digulirkan bertahun-tahun, tapi soal kesejahteraannya nampak tidak diberitakan, bahkan lebih menonjol soal keamanannya. Karena apa? benar kata Pak Jokowi, bahwa salah satunya adalah akses media ke Papua belum optimal dibukakan buat jurnalis asing. Karena dengan membuat Papua tertutup dari media, maka banyak orang akan sibuk menduga-duga dengan versinya sendiri-sendiri, seperti apa kondisi Papua? Media lebih sering menampakkan Papua dengan wajah korban kekerasan ketimbang pembangunan ekonomi.
Nah, ketika Pak Jokowi, bulan Mei kemarin datang ke Papua, secara tegas beliau mengatakan di depan kawan-kawan TNI, Polri, Masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, bahwa stop kekerasan, kita hentikan pendekatan represif, kita harus menggunakan pendekatan dialog damai, dan melakukan pendekatan secara sosial, ekonomi dan budaya. Pendekatan dengan hati.
Bahkan untuk urusan birokrasi pun juga seperti itu. Kadang kita lupa, di Jawa kita mungkin sibuk dengan urusan reformasi birokrasi yang canggih-canggih itu, tetapi di Papua jangan-jangan kawan-kawan disana tahapannya masih sedang belajar bagaimana birokrasi itu ditata dan bekerja. Kebutuhannya berbeda. Jika ukuran itu diseragamkan, selain kita tidak fair juga kita tidak akan mendapatkan gambaran besar persolan sebenarnya. Jadi, cara kita melihat Papua itu, harus dengan konteks papua itu.
Ketika saya menjadi staf seskab selama 8 bulan, saya melihat bahwa kita bisa berharap pada birokrasi pemerintah. Birokrasi kita perlu untuk mengubah mindsetnya dalam program pembangunan di Papua. Terlepas dari suka dan tidak suka, mesin birokrasi inilah yang bekerja untuk memastikan program presiden dilaksanakan. Diperlukan kepemimpinan yang kuat di tingkat kementerian dari menteri hingga eselon III-nya untuk menerjemahkan gagasan presiden secara kongkret. Kalau perlu kita harus membumikan dan mengkonkretkan bahasa birokrasi yang kadangkala tidak operasional dan sulit mencari indikatornya. Tetapi mengubah mindset yang sudah berpuluh-puluh tahun itu tidak mudah. Jadi yang kita butuhkan adalah menteri atau pemimpin yang memiliki terobosan agar program prioritas presiden dapat direalisasikan.
Berarti dalam implementasi di lapangannya masih ada hambatan dari birokrasi ini?
JP: Iya, tapi itu justru itu tantangannya. Masih banyak orang-orang baik di birokrasi yang dapat diandalkan. Harus diakui kalaupun ada kelemahan, bukan hanya birokrasi di tingkat Jakarta atau pusat, tetapi di pemerintahan daerah juga seperti itu. Seperti yang saya contohkan tadi, kita berbicara tentang birokrasi seakan seluruh Indonesia pemahamannya sama dan seragam, padahal di Papua sendiri birokrasi masih sederhana dipahami. Karena begini, kasarnya di Papua itu belajar tentang birokrasi pemerintahan itu khan belum selama seperti di Jawa atau di tempat-tempat lain selain Papua. Jadi kalau ukuran yang kita kenakan di Papua sama dengan yang kita kenakan di pusat itu kita akan mendapatkan jarak yang begitu berbeda, dan itu sepereti yang sudah saya katakan sebelumnya, rasanya tidak fair juga, menetukan keberhasilan dari tingkat itu, padahal kita melihat SDM nya, infrastruktur dan segala macamnya itu kan masih timpang.
Jadi seperti apa sesungguhnya pemerintahan Jokowi mengidentifikasi permasalahan Papua? Apa persoalan yang paling dominan di dalamnya; pertahanan dan keamanan, ekonomi dan kesejahteraan, atau sosial budaya?
JP: Kita tidak bisa melihat Papua secara parsial seperti itu. Karena semuanya saling terkait dan saling mengunci. Kita melihat pendekatan dominannya selama ini selalu politik dan makro. Itu tidak salah. Tetapi ada pendekatan lain juga yang penting, misalkan pendekatan budaya. Apakah kita tahu, bahwa Papua itu memiliki tujuh wilayah adat yang sangat berbeda-beda dan suku satu dengan lainnya memiliki karakter yang beragam. Harusnya dalam membangun Papua kita mempertimbangkan perbedaan dan keragaman mereka itu. Misalnya; ada usulan kebijakan bahwa kita perlu membangun asrama bagi pelajar papua agar mereka dapat fokus belajar karena sulitnya menjangkau lokasi belajar. Untuk daerah tertentu mungkin berhasil, tetapi untuk daerah lainnya justru tidak dianjurkan. Karena ada fakta objektif yang menunjukkan bahwa masih ada konflik antara suku satu dengan yang lain yang tidak bisa didamaikan. Pemahaman kita terhadap peta persoalan Papua dari berbagai sudut pandang, penting untuk dilakukan. Selain itu, kita perlu stop stigmatisasi terhadap kawan-kawan Papua kita. Masyarakat Papua kerap diidentikkan dengan masyarakat yang gemar mabuk-mabukkan, pemalas, bodoh, separatis dan lain-lain. Stigmatisasi dan penghakiman semacam itu sangat dekat dengan hasrat kita untuk kemudian mengontrol dan menguasai. Generalisasi semacam itu membuat cara kita melihat Papua menjadi suram, pesimis, dan mengabaikan potensi luar biasa mereka menjadi tidak terlihat.
Nah harusnya kan dibalik cara melihatnya, kenapa mereka seperti itu?Jangan-jangan kita juga berkontribusi besar dalam menciptakan situasi itu?
Saya pernah ke Wamena, saya melihat bahwa dari pagi sampai malam banyak usia produktif mondar-mandir di jalan-jalan, tidak melakukan apa-apa. Saya sempat bingung. Kenapa seperti itu? karena faktanya memang di sana tidak ada lapangan pekerjaan yang dibukakan untuk mereka. Pemerintah daerah harus ikut bertanggung jawab tentang menciptakan lapangan pekerjaan untuk mereka, terutama untuk orang-orang mudanya karena mereka selalu rentan untuk diprasangkai dan dituduh sebagai pelaku kekerasan, stigmasisasi itu selalu dikenakan ke mereka. Tetapi jarang yang mempertanyakan kenapa mereka melakukan hal seperti itu?
Seperti mama-mama Papua, ekonomi mereka itu khan subsistensi, jadi mereka menanam di halamannya, dan kemudian dibawa ke pasar untuk kelangsungan hidup. Tetapi kenapa kita tidak memikirkan pemasarannya seperti apa? Mungkin sudah ada. Tetapi kita butuh banyak tindakan-tindakan kongkret yang seharusnya bukan datang hanya dari pusat, tetapi dari daerah, bagaimana memberdayakan ekonomi keluarga ini, harus dipikirkan. Jadi sekarang ini dengan dana otsus yang begitu besar, akhirnya orang melihat bahwa kita tidak bekerja tetapi dapat duit. Ngapain kita menanam sayur dan berkebun, toh tiap bulan juga kita dapat uang walaupun tidak besar jumlahnya (ratusan ribu). Jadi jangan sampai charity kita merusak kemandirian mereka yang merupakan budaya mereka. Dan itu di beberapa tempat sudah terjadi. Jadi membangun Papua itu saya rasa bukan hanya unsur belas kasihan, tetapi bagaimana kita juga melihat bahwa Papua itu juga punya daya juang sendiri, punya survival strategy yang seharusnya kita manfaatkan dan bisa kita optimalkan untuk membantu kemandirian mereka dan bukan sekedar mengasihani, karena dalam jangka panjang hal itu bisa merusak. Bisa memupuskan modal sosial mereka.
Suatu ironi juga, dengan dana otsus yang begitu besar sejak tahun 2001 sampai sekarang, dan ditambah juga kekayaan alam Papua yang luar biasa?
JP: Dalam draf RAPBN Tahun 2016 yang diajukan oleh presiden, alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp 7.765.059.420.000, sebelumnya Rp. 7 Trilyun. Dari jumlah itu untuk Provinsi Papua 70 persen atau Rp 5.435.541.600.000 dan untuk Provinsi Papua 30 persen atau Rp2.329.517.820.000. Jumlah itu cukup besar dan Otsus sudah berjalan 14 tahun, pertanyaannya, apa yang salah dengan ini semua?banyak kritik yang datang, yang mengatakan ternyata dana yang begitu besar tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat Papua. Ada juga yang menyoroti bahwa dari dukungan regulasi baru setengah jumlah peraturan perundang-undangan yang baru diterbitkan. Belum adanya Perdasi dan Perdasus yang diperlukan yang berakibat pada kesulitan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga. juga tata hubungan kelembagaan Pemerintahan daerah seperti hubungan antara Pemda, DPRP, dan Majelis Rakyat Papua (MRP dan MRPB) yang belum harmonis dan efektif, belum lagi konsolidasi proses kebijakan yang belum baik antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban dan lain-lain. Itu kita masih bicara tata kelola pemerintahannya, belum yang lain-lain.
Tapi ditengah pesimisme yang begitu besar itu kita juga harus fair menilai pembangunan di Papua. Banyak hal yang sudah dilakukan. Bahwa itu tidak dikabarkan media bukan berarti sama sekali tidak ada kemajuan disana.
Dalam hal pendidikan misalnya, pemerintah juga sudah melakukan hal-hal yang positif, Misalnya, dalam setiap tahun ada semacam beasiswa untuk kawan-kawan Papua baik di perguruan tinggi maupun sekolah menengah untuk disekolahkan ke pulau Jawa maupun pulau lainnya, dan itu merupakan salah satu perguruan tinggi dan sekolah negeri terbaik. Jadi adaquota untuk mereka bersekolah di tempat yang bagus, dan jumlahnya ada sekitar 1400-an dari tahun 2013. Selain itu, sekarang ini yang sedang ditingkatkan adalah tenaga-tenaga medis, dokter, bidan, guru-guru yang ditugaskan disana dengan perbaikan sistem pengiriman dan insentif yang diterima mereka.
Kalau tidak keliru, ada 30 persen dana otsus yang dialokasikan untuk pendidikan, dan 15 persen untuk kesehatan. Berarti ada 55 persen lagi yang bisa dimaksimalkan untuk affirmatif bidang ekonomi yang anda sebutkan tadi. Kira-kira bagaimana?
JP: Penjelasan kita melalui data dan statistik itu saya kira penting, tapi bukan yang terpenting, angka-angka itu hanya menunjukkan kepada kita tentang gambaran kasarnya saja. Di permukaan. Namun kita juga perlu bagaimana kualitas dan implikasinya buat masyarakat Papua secara kongkret. Apakah pembangunan fasilitas kesehatan yang puluhan jumlahnya itu punya korelasi positif dengan penurunan angka kematian ibu misalnya. Kita harus punya alat ukur yang bisa kita nilai bersama. Yang bisa kesepakati dan akui bersama bahwa di Papua terjadi perubahan baik akibat pembangunan yang dilakukan.
Makanya presiden Jokowi mengubah pendekatan yang selama ini dikeluhkan bersama itu, negara yang hadir dengan wajah kekerasan itu. Dan menginginkan dialog damai itu menjadi prioritas. Simbol yang dihadirkan presiden Jokowi salah satunya melalui pelepasan tapol melalui pemberian grasi. Kenapa grasi? Karena ini adalah proses tercepat yang bisa dlakukan presiden sebagai salah satu hak prerogatifnya. Pelepasan tapol karenanya perlu dibaca sebagai simbol kesungguhan presiden untuk meyakinkan bahwa pendekatan dialog dan rekonsiliasi perlu dibangun. Salah satu caranya adalah mempersilakan semuanya untuk menilai perubahan di Papua secara obyetif, yaitu membuka isolasi Papua dengan mempersilakan wartawan asing untuk meliput dan mengabarkan ke dunia bahwa Indonesia itu hadir juga disana.
Seperti bulan Mei kemarin, simbol kehadiran negara agar terbaca di negara tetangga terlihat ketika dari papua presidena langsung terbang ke Papua Nugini. mau menegaskan bahwa Indonesia itu hadir di sini (Papua_red). Karena kalau tidak salah hampir berssamaan dengan kunjungan presiden disana, Papua Nugini buat statemen tentang nasib Papua Barat. Saya rasa itu juga adalah simbol politik.
Dalam kaitan simbolik itu, ada rencana bangun istana (presiden) juga di sana?
JP: Bangun istana mungkin tidak. Namun begini, keinginan beberapa pihak untuk hadirnya sebuah lembaga semacam Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (OP4B) jaman presiden SBY memang ada. Kami sedang mengkaji kebutuhan akan hadirnya lembaga seperti itu dan akan melibatkan kawan-kawan papua dan stakeholders terkait. Karena diakhir masa tugas UP4B ada semacam review dari beberapa pihak yang memberikan masukan plus minusnya kelembagaan semacam ini, ada yang mengatakan bahwa fungsinya tidak optimal karena hanya sebatas kordinasi. Tetapi ada juga yang mengatakan ini diperlukan karena relatif berjalan baik. Jadi hasil review kemarin itu penting untuk dilihat kembali. Karena presiden Jokowi juga sangat hati-hati sekali untuk membangun lembaga baru. Karena sekarang ini kita juga punya banyak lembagayang tidak efekif. Jadi jika presiden sekarang banyak melakukan perampingan sebetulnya itu juga diletakkan dalam argumentasi: penting tidak ya keberadaan lembaga ini? Jadi artinya bukan hanya sekedar perampingan tapi kegunaan untuk merampingkan itu juga bagian dari argumentasi itu.
Kalau lembaga semacam ini dibentuk apa ada kemungkinan untuk melibatkan partisipasi yang lebih luas dari masyarakat sipil atau?
JP: Kalau OP4B dulu keanggotaannya melibatkan pemerintah dan non pemerintah dan ada juga dari masyarakat Papua sendiri yang mewakili. Saya rasa kalau lembaga itu nanti terbentuk lagi, itu memang harus representasi dari kebutuhan rakyat Papua dalam konteks percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat. Maksudnya lembaga ini bisa menjamin dan memastikan terlaksananya yang diinginkan Pak Jokowi. Tetapi tentang kapan dan seperti apa, harus dikaji dulu. Karena dulu kan itu pernah ada, dan hasil review itu ada plus minusnya. Apakah lembaga, ataukah pokja atau komisi, itu masih dibicarakan. Kita harus berubah.
Kita lanjut tadi mengenai sinyal Jokowi ke negara-negara tetangga itu, karena ada negara dalam MSG (Melanesian Spearhead Group) yang tampaknya turut mendukung Papua Merdeka?
JP: Sekarang ini, dalam dunia dimana batas-batas negara semakin kabur dan teknologi mendekatkan kita satu sama lain dalam hitungan detik, mindset kita dalam menangani papua harus berubah. Posisi Papua ini sangat strategis karena dia juga sudah terlanjur dikapitalisasi secara internasional, dan sense of crisis kita tentang Papua yang bisa merdeka sewaktu-waktu harus ditumbuhkan, agar kita memiliki perhatiaan lebih untuk memperbaiki kesalahan kita masa lalu. saya rasa melihat Papua hari ini berbeda dengan 10-20 tahun lalu. Melalui pergerakan kawan-kawan diaspora dalam memperjuangkan nasib masyarakat Papua di berbagai negara mengindikasikan bahwa harusnya kita tidak menganggap sepele persoalan serius semacam ini.
Saya rasa Pak Jokowi melihat ini sebagai hal yang strategis yah. Bahwa kita tidak jamannya lagi menutup Papua, bukan eranya lagi negara menciptakan misteri untuk memperkokoh kekuasaannya. Karena apapun yang ditutup ongkos sosialnya terlalu mahal dan pasti bisa keluar. Teknologi sudah demikian canggihnya. Justru Indonesia harus melihat itu sebagai tantangan yang perlu diupayakan jalan keluarnya. Misalnya disatu sisi pembangunan ekonomi, sosial, budaya dilakukan, tetapi juga perlu memperhatikan bagaimana teman-teman muda kita di Papua terutama yang pro dengan kemerdekaan dan memperjuangkan nasib Papua segala macam itu harus diajak bicara. Stigmatisasi atau pelabelan negatif seperti separatis atau semacamnya perlu dihilangkan. Mungkin ada bagusnya juga ketika Pak Jokowi berbicara soal dialog damai juga mempercakapkan hal-hal yang dianggap sensitif itu. Itu bukan perkara mudah. Bagaimana mungkin dengan lensa yang berbeda kita bisa berdialog? Dan seperti kata alm Muridan, dialog itu kan tidak pernah membunuh, jadi kenapa tidak coba kita lakukan. Bukan hanya Jakarta Papua, tetapi juga Jakarta-Jakarta melihat Papua, dan Papua melihat Jakarta.
Kita penting melakukan ini, distrust Antara Jakarta-Papua, Papua-Jakarta itu sudah luar biasa parah. Jadi kita harus mengurai benang kusutnya pelan-pelan, butuh waktu, dan tidak mungkin 10 tahun selesai. Tetapi itu satu-satunya cara agar kekerasan, kematian, dan lain-lain, bisa dikurangi.
Tetapi kenapa penanganan Papua ini masih identik dengan kekerasan?
JP: Saya rasa seperti ini, di Papua itu kan ada sumber daya alam yang luar biasa, dan bukan hanya direbutkan di tingkat nasional tetapi juga incaran banyak negara-negara luar, sebut saja Amerika, dan freeport adalah salah satu representasi dari salah satu kepentingan itu. Tapi itu kan sudah terjadi lama, untuk melindunginya aparat keamanan menjadi dominan dalam mengendalikan keamanan dan dalam tugas pengamanannya itu distorsi kerap rentan terjadi di lapangan. Kekerasan merebak di beberapa tempat. kemudian itu menyadarkan pada kawan-kawan Papua, kok ada ketidakadilan disini? kenapa mereka sang pemilik justru menjadi masyarakat yang termiskin. Kesadaran mereka itu hidup dan tumbuh dari melihat dan merasakan langsung.
Baru-baru ini Presiden Jokowi membebaskan Tapol/Napol Papua, salah satunya Filep Karma. Menurutnya, kurang lebih, ia percaya presiden Jokowi memiliki niat baik untuk menyesaikan persoalan Papua, tapi ada problem dengan lingkungannya atau lebih spesifik lagi dengan angkatan bersenjata kita (TNI/Polri) yang masih jadi masalah dalam menyelesaikan persoalan Papua. Apakah ini berhubungan dengan mindset tadi?
JP: Iya, tadi soal distrust. Itu kan hanya enak diomongan saja. Maksud saya begini kalau kita berbicara mengenai operasionalisasi konsep, apa sih yang dimaksud dengan distrust? bagaimana soal konsistensi, karena distrust itu juga bicara soal konsistensi. Misalnya Jokowi bicara membuka isolasi media massa, tetapi kenyataannya Human Rights Watchmengatakan belum terjadi, misalkan seperti itu. Nah itu kan di mata masyarakat Papua kemudian bisa terjadi distrust pada Pak Jokowi, dan itu bisa saja. Tetapi kan ukuran distrust itu harus jelas, dalam artian begini: apa sih yang membuat ketidakpercayaan akut antara Papua-Jakarta dan Jakarta-Papua? Karena masing-masing di belakang kepalanya mempunyai segala macam prasangka yang susah diakurkan. Nah, satu-satunya jalan kenapa. Itu penting karena melalui dialog itu orang akan “dipaksa” bicara tentang perbedaan. Bicara tentang prasangka. Untuk mempercakapkan itu kan posisi masing-masing pihak harus setara. Sementara dulu konsep dialog pernah ditolak. Karena punya implikasi strategis, karena dialog itu berarti kita tunduk pada separatis dan kompromi kepada mereka. Padahal kan tidak seperti itu.
Dialog menurut Jokowi menjadi hal yang penting karena itu bisa memperdamaikan hal-hal yang di belakang kepala kita itu belum selesai karena prasangka-prasangka dan ketidakpercayaan.
Terakhir, soal Freeport. Ada keramaian di luar tentang “catut nama” dan “perpanjangan kontrak”, bagaimana Presiden melihat ini?
JP: Jadi kalau soal freeport yang diributkan itu, Pak Jokowi sudah clear sejak awal bahwa perpanjangan kontrak itu diomongin tahun 2019. Karena 2021 kan akan berakhir. Kalau soal konstitusi dan UU beliau konsisten kok. Jadi tidak mau ngomongin sebelum tahun 2019.
Sumber Artikel: http://www.berdikarionline.com/jaleswari-soal-papua-perlu-mengubah-mindset-dalam-pendekatan-dialog/#ixzz3wLubHvOz
Follow us: @berdikarionline on Twitter | berdikarionlinedotcom on Facebook

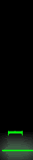

0 komentar:
Posting Komentar