Merenungkan Perdamaian dan Keadilan
Pada 2-3 Desember saya menghadiri lokakarya tentang perdamaian dan keadilan yang dibuat oleh International Center for Transitional Justice (ICTJ) di Hotel The LokhaLegian, Bali. Acara ini diikuti oleh 25 aktivis, mantan pejabat dan peneliti. Yang dari Indonesia datang dari Jakarta (Elsam, Komnas HAM, LIPI, ICTJ Jakarta), Aceh (Advisor Forbes dan aktivis Partai Rakyat Aceh), Maluku, dan Papua (Gereja Kingmi dan Dewan Adat Papua). Sedangkan yang dari luar negeri ada dari Timor Leste (Progressio dan Provedoria), Nepal (ICTJ Nepal), Swiss (ICTJ Geneva), dan lain-lain. Yang agak lain, saat itu hadir juga seorang jendral yang dikenal reformis, Agus Widjojo.
ICTJ mengajak kita merenungkan hubungan antara perdamaian dan keadilan. Keduanya dinilai sebagai tonggak penting dalam konteks paska konflik. Dalam praktiknya, keduanya seringkali dianggap bertentangan. Demi perdamaian, katanya, keadilan bisa ditunda atau bahkan diabaikan. Yang lain mengatakan, keadilan harus ditegakkan dulu baru perdamaian yang sejati bisa tercipta. Ada juga ketakutan, jika keadilan terlalu didorong, suasana perdamaian bisa terganggu. Pada kasus perdamaian Aceh, representasi politik yang lebih dulu dipecahkan daripada isu keadilan seperti pengadilan HAM dan rekonsiliasi. Pada kasus Papua keadilan sulit ditegakkan karena perdamaian belum terjadi. Papua masih terjebak di dalam ruang konflik.
Apakah perdamaian dan keadilan memang saling menegasikan? Pada saat pembukaan, Priscilla Hayner (ICTJ Geneva), menunjukkan kompleksitas hubungan keduanya. Setiap perdamaian di tingkat lokal, nasional, maupun internasional memiliki kekhasannya sendiri. Priscilla mengajak peserta belajar dari Nigeria, Sierra Leone, Nepal, dan lain-lain. Ternyata tidak ada model baku untuk keduanya. Theo van den Broek menegaskan bahwa di dalam setiap perdamaian itu sendiri terdapat unsur keadilan. Tidak bisa sekaligus ditegakkan, tetapi bertahap. Perjuangan keadilan harus diarahkan pada pencapaian full justice. Saya sendiri menambahkan bahwa hubungan perdamaian dan keadilan sangat bergantung pada hubungan kuasa yang ada. Pembuat perdamaian biasanya adalah pihak-pihak yang memiliki kuasa. Sedangkan korban biasanya tidak memilikinya.
Pandangan aktivis Maluku Anthony Hatane sangat menarik. Dibandingkan dengan Aceh dan Papua, mereka merasa tidak mendapatkan keadilan sama sekali. Perdamaian yang sudah terjadi tidak diikuti dengan penegakan keadilan melainkan dengan stigma separatis. Sejak perdamaian Malino II, tidak ada tindak lanjut sama sekali di sana. Aceh dan Papua lebih diistimewakan. Di Aceh ada konsesi politik yang luar biasa terhadap rakyat Aceh dengan UU 11/2006. Bahkan Hasan di Tiro pulang ke Aceh disambut dengan penuh hormat. Di Papua rakyatnya menikmati UU 21/2001 tentang otonomi khusus yang dananya sangat besar. Menurut saya, seringkali kita terpaku pada apa yang kurang dan lupa melihat pencapaian yang sudah diperjuangkan. Ini penting untuk menjaga agar semangat berjuang tetap terjaga.
Lalu, bagaimana dengan Papua? Apakah di Papua sudah ada perdamaian dan keadilan? Menurut saya, belum ada tanda signifikan bahwa keduanya sudah ada di Papua. Konflik politik masih berlangsung antara Jakarta dan Papua. Stigma dan permusuhan masih kuat. UU Otsus meskipun substansinya bagus tidak mendapatkan legitimasi dari kedua pihak yang berkonflik. Dua-duanya sama-sama curiga dan sama-sama tidak percaya. Yang satu bilang Otsus itu agenda tersembunyi separatis. Yang lain bilang, Otsus itu gula-gula tipu dari Jakarta. Pada tataran obyektif, kita tahu bahwa orang asli Papua masih termarjinalisasi, pembangunan gagal, penegakan HAM tidak juga dimulai, dan sumber konflik tentang sejarah tidak juga disentuh.
Pada kesempatan lokakarya itu, saya mengatakan bahwa konflik Papua harus diakhiri dengan suatu pakta perdamaian, entah melalui dialog atau musyawarah, agar kita semua keluar dari tahapan konflik dan masuk pada tahapan paska konflik. Kesepakatan baru bisa dibuat untuk menuju Papua Baru. Dengan itu, UU 21/2001 bisa direvisi berdasarkan kesepakatan para pihak. Stigma separatis bisa dihapus. Operasi militer dan intelijen yang mengganggu rasa aman penduduk di Papua segera diakhiri. Dalam suasana seperti itu kita bisa menjalankan Papua Road Map seperti yang sudah diterbitkan oleh LIPI. Jakarta dan Papua bisa memulai hubungan politik baru yang lebih konstruktif dan bersama-sama menyejahterakan penduduk di Papua.
(Photo: Priscilla Hayner dan saya sedang diskusi, oleh Edisius Riyadi, 2008)

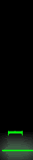

0 komentar:
Posting Komentar